Matanya yang besar menyala menatapku dalam sikap curiga. Ada dua buah tanduk kecil yang mencuat dari kepalanya. Kulitnya tampak kasar bersisik. Aku bisa melihat sepasang sayap yang melipat di balik bahunya. Ia masih sangat kecil kala itu, dan kutemukan suatu malam meringkuk di bawah tempat tidurku. Aneh memang, jika aku tak memiliki rasa takut berlebih, sebagaimana seorang anak-anak melihat sesosok wujud yang mengerikan. Sebab begitulah adanya aku ketika melihatnya, dan untuk kemudian mengganggap ia sebagai teman kecil yang menyenangkan.
Begitulah ia suatu ketika dalam memulai cerita, sebagaimana yang pernah mereka ingat. Dan hingga kini, cerita itu masih berlanjut. Selalu saja ada kanak-kanak sekitar yang menyediakan diri di samping kursinya, untuk sekadar bermanja-manja dengan setiap ceritanya. Anak-anak itu selalu terlihat begitu seksama dalam mendengarkan cerita-ceritanya. Duduk bersila dengan tatap tak berkedip, memandang seorang perempuan yang bercerita dengan ekspresi yang demikian sempurna. Dan itu membuat kanak-kanak itu tampak jauh lebih khidmat, dibanding dengan menyaksikan film-film kartun di setiap sore akhir pekan.
Tak pernah ada yang mengingat kapan perempuan itu mulai mendendangkan cerita-cerita tentang naga. Seakan-akan semua itu telah berlangsung selama berpuluh tahun hidupnya. Di setiap senja, ia akan bersiap di beranda di atas kursinya. Memanjakan diri dengan rajutan benang wol yang seakan tak pernah kunjung selesai. Sembari menunggu kanak-kanak yang tak berapa lama akan datang berduyun-duyun tiba, untuk mendengarkan sebuah cerita tentang seekor naga yang dipeliharanya. Selalu saja tentang naga, yang ia ceritakan dengan jalan cerita yang setiap kali berbeda. Pada suatu ketika, ia bercerita tentang naganya yang sakit keras, sehingga ia harus membuat sebuah ramuan khusus dari jamur-jamuran langka untuk mengobatinya. Kali lain, ia berkisah tentang naganya yang pemurung. Dan ia harus menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal konyol, agar naga itu kembali ceria. Demikianlah, anak-anak itu tak pernah mendengar bentuk cerita yang sama di setiap senja. Dan itu akan membuat mereka senang, serta datang kembali di keesokan harinya.
Setiap hari di setiap senja, perempuan itu selalu bercerita tentang naga yang dipeliharanya. Tak pernah ada senja yang terlewat. Aneh memang, jika anak-anak yang datang dalam setiap harinya terkadang ada yang tak datang karena sakit atau alasan lain, maka perempuan itu tak pernah sekalipun meninggalkan kewajibannya untuk bercerita di setiap senja. Anak-anak pun mulai membangun ceritanya sendiri, bahwa perempuan itu telah mendapat berkah dari Tuhan karena memelihara naga, dan karenanya ia terjaga dari sakit atau luka. Belakangan, anak-anak itu pun percaya, bahwa perempuan itu tak pernah bertambah usia. Ia selalu tampak begitulah adanya, dalam waktu yang seakan membeku di wajahnya. Mereka membanding-bandingkannya dengan orang-orang tua mereka, yang kini mulai tampak renta dengan kulit keriput dan warna putih di rambutnya.
Sejak menemukannya, aku memeliharanya di dalam kamarku untuk memudahkanku merawatnya. Perlu kalian ketahui, ia bukan sejenis naga yang tumbuh menjadi sebesar gunung atau bukit. Nagaku seakan hanya mampu tumbuh sebesar ranjang tidurku, dan itu membuatku cukup untuk menyimpannya di kamarku. Tapi percayalah, dengan tubuh seukuran itu, ia akan mampu melahap tubuh orang dewasa dengan sekali telan. Giginya sangat runcing untuk mengoyak daging manusia. Dan tidak lupa, nagaku punya cakar yang lebih tajam dari milik serigala jenis apapun. Tapi jangan khawatir, ia cukup jinak untukku. Dan tanpa ijinku, tak akan kubiarkan ia lepas dari kamarku walau untuk semilimeterpun. Karena itu, aku tak akan mempertunjukannnya pada kalian. Aku hanya akan menceritakannya, maka dengarkanlah ceritaku baik-baik.
Begitulah kemudian, ia akan bercerita kepada anak-anak yang mengelilinginya. Dan anak-anak itu seakan terpedaya, memasang telinga dan tatap mata mereka hanya pada kata-kata dan wajah perempuan yang akan bercerita. Mula-mula, cerita itu akan dimulai dari bagaimana ia menemukan naga itu di bawah tempat tidurnya. Kemudian, dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang ia alami dalam memeliharanya. Cerita itu lalu mengalir begitu saja, seakan sebuah kisah seribu satu malam yang tiada habisnya. Dan bayangkan pula, bila perempuan dan anak-anak itu harus menceritakan dan mendengarnya pula di setiap hari di setiap senja. Anehnya, mereka tak tampak bosan atau kelelahan. Bahkan, perempuan itu kadang harus menjawab pula beberapa pertanyaan lugu anak-anak tentang naga yang dipeliharanya.
“Apakah nagamu memiliki nama?”
“Tidak. Aku hanya menyebutnya ‘naga kecil’.”
“Berapakah umurnya?”
“Seumur denganku.”
“Apakah ia laki-laki?”
“Ya, ia naga jantan.”
“Ia kau beri makan apa?”
“Daging yang aku beli dari pasar.”
“Apakah ia tidak bosan terus menerus berada di kamar?”
“Kadang kami keluar juga, tapi tak seorang pun yang bisa melihatnya. Kadang ia juga terbang sesuka hati untuk kemudian kembali.”
“Apakah kau pernah menungganginya untuk terbang?”
“Pernah, tapi ia tak begitu suka ditunggangi.”
“Apakah ia suka menyemburkan api?”
“Ya, kalau marah ia suka menyemburkan api.”
“Apakah ia bisa berbicara?”
“Ya, ia bisa bicara dengan bahasa yang berbeda.”
“Apakah nagamu tidur mendengkur seperti ayahku?”
“Sedikit.”
“Apakah kami bisa memegangnya?”
“Tidak, kau akan dilahapnya.”
“Kalau kau bisa, mengapa kami tidak?”
“Karena aku adalah perempuan yang diberkati Tuhan untuk memeliharanya, sedang kalian tidak.”
“Siapa yang mengirimkan naga untukmu?”
“Entahlah, mungkin Tuhan.”
“Apakah kami bisa memiliki naga juga?”
“Mintalah pada Tuhan, mungkin Ia berkenan mengirimkannya untukmu.”
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan datang bertubi-tubi, yang selalu dijawabnya pula dengan kesabaran yang bersahaja. Tapi perempuan itu hanya memberi kesempatan anak-anak itu untuk bertanya pada awal dan akhir cerita, demi tidak untuk menyelanya di tengah cerita. Dan hingga matahari telah benar-benar tenggelam, seluruh cerita tentang naga pun usai. Selalu begitu tepat waktu seakan setiap cerita telah diatur sedemikian cermat. Maka berhamburanlah anak-anak itu menuju jalan pulang. Memenuhi panggilan orang tua mereka yang telah berteriak-teriak dengan nada muram. Dengan bayang-bayang, cerita apakah yang akan mereka dapatkan di esok petang.
***
Tak pernah ada orang tua yang melarang anak-anak mereka untuk mendengarkan cerita tentang naga dari perempuan itu. Sebagaimana juga tak pernah ada orang tua yang sungguh-sunggguh percaya bahwa perempuan itu memelihara naga. Orang-orang sekitar hanya menganggap itu sebagai bualan besar yang disenangi kanak-kanak. Sebagai penenang anak-anak mereka agar tidak lagi berkelahi, bermain di jalan-jalan, atau mencuri bebuahan di pohon tetangga di setiap senja. Lagipula, hingga kini tak pernah ada yang benar-benar menyaksikan dengan langsung kehadiran naga itu di rumahnya. Entah sekadar dengusan nafas besar, eraman keras, atau pun mata merah besar menyala di jendela. Begitulah seterusnya anggapan mereka hingga berpuluh tahun ini.
Bahkan, adapula orang-orang yang menganggap ia sebagai perempuan gila. Didorong oleh pemikirian bahwa keterasingan dan keterkucilan dari masyarakat sekitar akan menjelma racun jiwa bagi siapapun, terlebih untuk perempuan itu. Sebab perempuan itu seorang penyendiri dan tak pernah mau beramah tamah dengan orang-orang sekitar, kecuali anak-anak yang datang untuk mendengar ceritanya di setiap senja. Orang-orang sekitar pun menjauhinya karena perempuan itu sering berlaku tak biasa. Terkadang perempuan itu seakan berbicara entah dengan siapa. Dan ketika orang-orang bertanya, ia menjawab dengan bahasa yang tak dimengerti oleh siapa-siapa. Akhirnya, orang-orang sekitar pun membiarkannya hidup sendiri, tak pernah ada lagi yang peduli, selain tentu saja anak-anak yang mendengar ceritanya setiap senja. Walau demikian, sebagaimana anak-anak itu, adapula sebagian orang-orang yang sedikit bersimpati padanya. Kebanyakan adalah kaum perempuan, didorong oleh kepedulian sesama kaumnya. Namun, tentu saja mereka terlalu takut untuk mengungkapkannya. Lebih mudah hanya berdoa untuk keselamatannya, dibanding resiko untuk ikut dianggap gila. Dan terlepas dari tingkah laku perempuan itu yang tak biasa. Ia hanya seorang perempuan yang bersahaja. Selalu tampil rapi dengan rambut lurus menjuntai dan harum pada tubuhnya. Pakaian berendanya selalu berwarna hitam. Tentu ia memiliki alasan, tapi tidak untuk dikatakan.
Perempuan itu tak memiliki keluarga pula. Kedua orang tuanya pergi tiba-tiba dengan menyisakan sebuah rumah dan kekayaan yang mungkin cukup untuk seumur hidupnya. Hanya ada seorang teman jauh ibunya yang kadang-kadang mengunjunginya. Didorong atas keinginan balas budi karena orang tua perempuan itu telah menyelamatkan nyawanya entah dari apa. Perempuan itu hanya menyebut teman ibunya itu dengan sebutan Sang nenek. Mungkin dengan alasan bahwa teman ibunya itu memang telah tampak renta. Dan sebagaimana pernah diakuinya kepada anak-anak yang selalu mendengar ceritanya, bahwa ia tak mengenalnya sama sekali. Sang nenek akan berkunjung di waktu-waktu tak tentu. Dengan membawa beberapa jenis makanan ringan dan benda-benda seadanya. Kemudian selalu menyempatkan diri bermalam untuk beberapa hari. Sementara perempuan pemelihara naga itu hanya menggapnya sekadar Sang nenek jauh yang datang berkunjung seperti biasa. Didasari penghormatan dan kenyataan bahwa Sang nenek adalah teman baik orang tuanya. Lagipula tak pantas rasanya bila ia berlaku kurang ajar pada seorang wanita yang telah tua itu, misalnya dengan mengusir atau memintanya pulang.
Namun itu pula yang mengakhiri segalanya. Sebagaimana kemudian ketahui oleh orang-orang. Dan sesungguhnya, sebuah perpisahan telah diisyaratkan oleh perempuan itu kepada anak-anak yang selalu mendengar ceritanya setiap senja. Tapi terlalu dini bagi anak-anak itu untuk mengerti.
Malam tadi, aku bertemu kedua orang tuaku dalam mimpi. Ini hal yang tak pernah aku alami sebelumnya. Telah lama aku merindukan mereka. Karena sebagaimana kalian tahu, aku tak memiliki seorang pun keluarga, selain naga kecilku dan kalian sahabat-sahabatku. Kedua orang tuaku meninggalkanku sedari usiaku belum cukup matang mengarungi hidup. Entah mengapa dan kemana. Hanya foto-foto usang dan harta benda yang mereka tinggalkan. Aku kini sedih, sangat sedih. Aku sangat merindukan kedua orang tuaku, mungkin begitu pula kedua orang tuaku. Ah, sepertinya naga kecilku pun telah cukup usia untuk memelihara dirinya sendiri.
***
Akhirnya, tak ada lagi kanak-kanak yang datang setiap senja ke beranda rumahnya. Hal itu bukan tanpa sebab. Suatu hari, perempuan itu ditemukan terkapar di rumahnya dengan kepala berlumuran darah. Nyawanya kemudian tak terselamatkan. Hasil autopsi menghasilkan temuan seadanya, bahwa kematiannya disebabkan pukulan benda keras tumpul di kepala. Sebagaimana kemudian ditemukan sebuah guci tua yang pecah berhamburan dan berlumurkan darah, diduga sebagai alat pemukul yang menyebabkan kematiannya. Tubuh tak bernyawa perempuan itu ditemukan oleh Sang nenek ketika waktu menunjukan pagi tiba.
“Itu saat ketika aku hendak mengantarkan sarapan paginya.”
Begitulah keterangan Sang nenek. Tetapi polisi terlalu bercuriga. Itu terlalu dini untuk sebuah sarapan pagi. Dan setelah melalui sederatan investigasi dan penyidikan yang sempurna, kenyataan itu akhirnya terungkap. Motif rakus harta benda menjadi akar mulanya. Sang nenek menduga bahwa keluarga itu menyimpan sebuah harta karun berwujud peti berisi penuh emas di kamarnya. Itu disebabkan karena orang tua perempuan itu adalah suami istri yang telah melakukan pencurian sebuah peti berisi emas dari sebuah bank puluhan tahun lalu. Sang nenek pula yang telah membunuh kedua orang tua perempuan itu, dan menguburnya di halaman belakang rumahnya. Dan selama ini, ia menutupi kebohongan itu dengan berbaik hati mengunjungi perempuan itu, agar suatu ketika bisa menemukan di mana letak penyembunyian emas itu berada.
Namun, sekian tahun berlalu, setelah ia menggeledah sebagian besar rumah itu dengan berpura-pura datang berkunjung, peti berisi emas itu tak juga kunjung ditemukan. Dan hanya satu tempat yang belum terjamah, yaitu kamar sang perempuan. Perempuan itu selalu berdalih ada seekor naga di kamarnya, dan karena itu ia tak akan mempersilahkan seorang pun masuk. Tak terkecuali, Sang nenek perayu yang selama ini berbaik hati padanya.
“Naga itu tak terlalu jinak untuk selain diriku. Bahkan seekor kucingku dilahapnya. Aku tak mau kau mati karena itu,” ujar perempuan itu beralasan.
Namun sebagaimana ketidakpercayaan semua orang, Sang nenek tahu itu hanya omong kosong belaka. Sebab ia tak penah benar-benar menyaksikan isyarat kehadiran naga di kamar perempuan itu selama berpuluh tahun. Pasrah karena perempuan itu tak bisa diperdaya dengan bujuk rayu, Sang nenek menyiapkan rencana selicik ular dan sejahat serigala. Sebelumnya, ia hanya bermaksud membuat perempuan itu tak sadarkan diri, dan kemudian menggeledah kamarnya demi peti berisi emas itu. Namun, kenyataan berbicara lebih. Maka terjadilah yang telah terjadi. Dan perempuan sang pemelihara naga itu kehilangan nyawa, dengan bermandikan darah di kepalanya.
Sebagaimana kemudian yang diketahui orang-orang. Emas itu tidak juga ditemukan. Hanya saja pertanyaan mulai muncul di benak orang-orang sekitar, setelah tiba sebuah berita mengejutkan. Sang nenek pun mulai gila di tengah penghukumannya. Dan pada saat-saat terakhir, ia telah meneriakan sesuatu yang lebih jahat dari dosa-dosanya.
“Ada naga di kamar perempuan itu. Matanya yang besar menyala menatapku dalam sungguh murka. Dia tahu bahwa aku telah membunuh tuannya. Dua buah tanduk tajam yang mencuat dari kepalanya adalah untuk merobek tubuhku. Cakar di kedua lengannya bersiap untuk mencengkram kepalaku. Kedua sayapnya yang lebar membentang adalah untuk terbang mengejarku. Ia bersumpah hendak membunuhku pada malam purnama ke tiga puluh. Tolonglah! Aku akan mati karena naga peliharaan perempuan itu. Ia akan memburuku!”
Sebagaimana dengan pemikirannya dulu. Semua orang mengganggap itu hanya sebagai bualan kosong belaka. Hingga pada suatu pagi, setelah malam purnama ketiga puluh, orang-orang menemukan hal yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Di dalam penjara, Sang nenek itu ditemukan tewas mengerikan dengan tubuh terkoyak, kepala hancur, dan beberapa bagian tubuh lain terbakar hangus serta berserakan seperti tercabik. Tak ada jejak lain dari sang pembunuh. Hanya menyisakan tapak besar berlumur darah kental di lantai. Semacam tapak naga pembunuh.
Bandung, 12062006, 05:22
31 August 2006
BACA AJA DECH ......
Era globalisasi telah demikian berkembang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industri semakin tak terbayangkan. Di satu sisi, hal tersebut merupakan bukti bahwa kita memiliki kemampuan untuk terus bergerak dinamis dan melaksanakan pertumbuhan. Adapun pada keyataannya, hal tersebut memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan misalnya, kualitas pendidikan semakin meningkat seiring berkembangnya dan terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang semakin memadai demi kelancaran dan suksesnya kegiatan proses pembelajaran. Dalam bidang lainnya, sistem ekonomi agraris yang bersifat tradisional, lambat laun bergeser menuju sistem ekonomi industrial yang lebih modern.
Akan tetapi, setiap perubahan selalu menyimpan dua sisi, baik sisi positif, maupun sisi negatif. Demikian pula dengan pesatnya roda globalisasi serta dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tak mampu mengelak dari dampak yang ditimbulkannya, baik positif, maupun negatif. Dampak positifnya telah kita rasakan berupa peningkatan kualitas kehidupan di beberapa bidang semisal teknologi, industri, ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Berbagai hal tersebut merupakan buah dari kerja keras yang layak mendapat penghargaan. Bukankah Allah swt. dalam Al Quran surat Ar Ra’du telah berfirman bahwa Ia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Demikianlah kita, telah berupaya menentukan jalan untuk masa depan kita sendiri dengan perubahan.
Walau demikian, sisi negatif yang timbul dibalik kilau kemajuan teknologi industri serta pesatnya globalisasi ternyata perlu kita khawatirkan. Betapa tidak, kemajuan yang kita kecap ternyata juga menimbulkan pergeseran terhadap nilai-nilai dan standar moral yang selama ini kita anut. Tanpa sadar, lambat laun kita diseret untuk semakin menjauh dari cita-cita etika yang ingin kita capai, bahkan dari yang telah kita capai. Karenanya, timbulah setumpuk problematika yang tak dikenal sebelumnya, yang tanpa sadar mengancam keberlangsungan kemapanan peradaban manusia.
Perbincangan tentang krisis moral kemudian menjadi sedemikian utama. Hal ini dikaitkan dengan prilaku masyarakat, khususnya generasi muda, yang seakan tak lagi mengenal batas. Hak untuk kebebasan menjadi dalih dan pembenaran terhadap setiap tindakan. Ajaran agama dan etika yang seharusnya jadi panutan seketika lumer oleh silaunya modernisasi yang kebarat-baratan. Generasi muda bangsa tak lagi berkehendak untuk menampilkan lagi moralitas dan etika ketimurannya.
Hedonisme, materialisme, dan sikap konsumtif menjangkiti setiap gerak masyarakat sebagai akibat kurang kokohnya benteng moralitas diri. Generasi muda pun mulai gandrung terhadap budaya funky, trendy, modies, hingga seks bebas. Hal tersebut sejalan pula dengan maraknya narkotika, alkohol, obat-obatan terlarang, dan penyakit moral lainnya. Semua ini menunjukan betapa telah terpuruknya generasi bangsa, serta adalah tugas yang teramat berat untuk menyembuhkannya.
Degradasi moral generasi muda tersebut tak lepas dari kewaspadaan orang tua yang karena pergeseran budaya lambat laun menjadi semakian abai. Para orang tua dijejali dengan berbagai kesibukan yang diluar batas kewajaran demi kepentingan materi belaka hingga tak ada waktu tersisa untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan putra-putri mereka. Curahan kepedulian lebih sering difokuskan pada hal-hal yang bersifat keduniawian, sementara kebutuhan aspek batiniah dan kasih sayang semakin jauh dari pengamatan. Hal ini tentu berefek buruk bagi prilaku dan sikap generasi muda dalam menjalani kehidupan. Tak heran jika kehidupan mereka kian tidak terkontrol dan jauh dari harapan hidup lebih baik.
Mencermati fenomena tersebut, perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasinya. Beberapa hal mungkin bisa dijadikan alternatif dasar pemecahannya. Pertama, penyadaran peran orang tua sebagai pendidik. Dalam hal ini, fungsi orang tua dalam memberikan pencerahan terhadap putra-putrinya menjadi sangat penting. Orang tua harus selalu menanamkan ajaran-ajaran kebaikan, baik itu bersumber dari ilmu-ilmu agama, maupun etika yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut tidak hanya meliputi aspek pemahaman akan tetapi lebih pada tataran aplikasi, misalnya dengan memberikan teladan prilaku dan sikap yang baik. Curahan kasih sayang dalam suasana kekeluargaan bisa dijadikan jalan untuk lebih mendekatkan sikap saling pengertian hingga sang anak bisa lebih nyaman untuk menempatkan dirinya dalam didikan orang tua.
Kedua, optimalisasi lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan, sekolah misalnya, harus mampu memberikan segenap fasilitas untuk tumbuh berkembangnya kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual anak didik. Lembaga sekolah harus memaksimalkan fungsinya sebagai kelanjutan dari peran orang tua sebagai pendidik. Apabila berbagai optimalisasi tersebut berjalan baik, maka anak didik, dalam hal ini generasi muda, akan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, selain juga mempunyai kematangan emosional dan kemapanan spiritual yang baik.
Ketiga, keterlibatan lingkungan masyarakat. Sebagai lingkup terluas dalam kehidupan sosial, masyarakat memegang peran penting untuk menentukan kepatutan prilaku generasi muda. Lingkungan masyarakat hendaknya menjadi wadah yang mampu melayani segala potensi dan memberikan ruang gerak yang cukup untuk perkembangan generasi muda. Masyarakat diharapkan mempunyai kepahaman dengan apa yang menjadi harapan lembaga pendidikan dan keluarga. Selain itu, lingkungan masyarakat sepatutnya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada generasi muda untuk mengemban amanat dalam kehidupan sosial.
Dengan pensinergian ketiga hal di atas, akan lahir generasi muda yang tangguh mempertahankan diri dari ancaman dampak negatif globalisasi, tidak sebaliknya, menyerah kalah dan terjerumus dalam terkaman degradasi moral yang akut. Wallahu Aa’lam bishshawab.
Akan tetapi, setiap perubahan selalu menyimpan dua sisi, baik sisi positif, maupun sisi negatif. Demikian pula dengan pesatnya roda globalisasi serta dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tak mampu mengelak dari dampak yang ditimbulkannya, baik positif, maupun negatif. Dampak positifnya telah kita rasakan berupa peningkatan kualitas kehidupan di beberapa bidang semisal teknologi, industri, ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Berbagai hal tersebut merupakan buah dari kerja keras yang layak mendapat penghargaan. Bukankah Allah swt. dalam Al Quran surat Ar Ra’du telah berfirman bahwa Ia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Demikianlah kita, telah berupaya menentukan jalan untuk masa depan kita sendiri dengan perubahan.
Walau demikian, sisi negatif yang timbul dibalik kilau kemajuan teknologi industri serta pesatnya globalisasi ternyata perlu kita khawatirkan. Betapa tidak, kemajuan yang kita kecap ternyata juga menimbulkan pergeseran terhadap nilai-nilai dan standar moral yang selama ini kita anut. Tanpa sadar, lambat laun kita diseret untuk semakin menjauh dari cita-cita etika yang ingin kita capai, bahkan dari yang telah kita capai. Karenanya, timbulah setumpuk problematika yang tak dikenal sebelumnya, yang tanpa sadar mengancam keberlangsungan kemapanan peradaban manusia.
Perbincangan tentang krisis moral kemudian menjadi sedemikian utama. Hal ini dikaitkan dengan prilaku masyarakat, khususnya generasi muda, yang seakan tak lagi mengenal batas. Hak untuk kebebasan menjadi dalih dan pembenaran terhadap setiap tindakan. Ajaran agama dan etika yang seharusnya jadi panutan seketika lumer oleh silaunya modernisasi yang kebarat-baratan. Generasi muda bangsa tak lagi berkehendak untuk menampilkan lagi moralitas dan etika ketimurannya.
Hedonisme, materialisme, dan sikap konsumtif menjangkiti setiap gerak masyarakat sebagai akibat kurang kokohnya benteng moralitas diri. Generasi muda pun mulai gandrung terhadap budaya funky, trendy, modies, hingga seks bebas. Hal tersebut sejalan pula dengan maraknya narkotika, alkohol, obat-obatan terlarang, dan penyakit moral lainnya. Semua ini menunjukan betapa telah terpuruknya generasi bangsa, serta adalah tugas yang teramat berat untuk menyembuhkannya.
Degradasi moral generasi muda tersebut tak lepas dari kewaspadaan orang tua yang karena pergeseran budaya lambat laun menjadi semakian abai. Para orang tua dijejali dengan berbagai kesibukan yang diluar batas kewajaran demi kepentingan materi belaka hingga tak ada waktu tersisa untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan putra-putri mereka. Curahan kepedulian lebih sering difokuskan pada hal-hal yang bersifat keduniawian, sementara kebutuhan aspek batiniah dan kasih sayang semakin jauh dari pengamatan. Hal ini tentu berefek buruk bagi prilaku dan sikap generasi muda dalam menjalani kehidupan. Tak heran jika kehidupan mereka kian tidak terkontrol dan jauh dari harapan hidup lebih baik.
Mencermati fenomena tersebut, perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasinya. Beberapa hal mungkin bisa dijadikan alternatif dasar pemecahannya. Pertama, penyadaran peran orang tua sebagai pendidik. Dalam hal ini, fungsi orang tua dalam memberikan pencerahan terhadap putra-putrinya menjadi sangat penting. Orang tua harus selalu menanamkan ajaran-ajaran kebaikan, baik itu bersumber dari ilmu-ilmu agama, maupun etika yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut tidak hanya meliputi aspek pemahaman akan tetapi lebih pada tataran aplikasi, misalnya dengan memberikan teladan prilaku dan sikap yang baik. Curahan kasih sayang dalam suasana kekeluargaan bisa dijadikan jalan untuk lebih mendekatkan sikap saling pengertian hingga sang anak bisa lebih nyaman untuk menempatkan dirinya dalam didikan orang tua.
Kedua, optimalisasi lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan, sekolah misalnya, harus mampu memberikan segenap fasilitas untuk tumbuh berkembangnya kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual anak didik. Lembaga sekolah harus memaksimalkan fungsinya sebagai kelanjutan dari peran orang tua sebagai pendidik. Apabila berbagai optimalisasi tersebut berjalan baik, maka anak didik, dalam hal ini generasi muda, akan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, selain juga mempunyai kematangan emosional dan kemapanan spiritual yang baik.
Ketiga, keterlibatan lingkungan masyarakat. Sebagai lingkup terluas dalam kehidupan sosial, masyarakat memegang peran penting untuk menentukan kepatutan prilaku generasi muda. Lingkungan masyarakat hendaknya menjadi wadah yang mampu melayani segala potensi dan memberikan ruang gerak yang cukup untuk perkembangan generasi muda. Masyarakat diharapkan mempunyai kepahaman dengan apa yang menjadi harapan lembaga pendidikan dan keluarga. Selain itu, lingkungan masyarakat sepatutnya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada generasi muda untuk mengemban amanat dalam kehidupan sosial.
Dengan pensinergian ketiga hal di atas, akan lahir generasi muda yang tangguh mempertahankan diri dari ancaman dampak negatif globalisasi, tidak sebaliknya, menyerah kalah dan terjerumus dalam terkaman degradasi moral yang akut. Wallahu Aa’lam bishshawab.
22 August 2006
Aku Serupa Malam
 Hari ini aku ingin menjumpai seseorang, berkata-kata, mengungkapkan sebuah penyesalan, sekadar rasa bersalah, atau mungkin apa saja. Namun, mengapa tiba-tiba aku serasa kehilangan setiap alasan untuk setiap tindakan. Serupa malam yang kian sunyi dan dingin. Aku menggigil. Tercerabut dari sesuatu yang tak bernama, tak berasa, tak bentuk, namun mengada. Lalu di mana kau, tempat aku berkisah. Tatapku tak mampu menemukanmu dalam rerimbun kabut. Aku harus mengucap banyak pengakuan hari ini. Tak mampu lagi kubendung. Sungguh. Maafku untuk setiap sisi gelapku, karena kita tak pernah benar-benar menginginkan semua itu terjadi. Pun diriku sendiri, itu benar. Angin yang mengirimkannya tiba-tiba, tanpa sepengetahuan siapa pun. Terlebih diriku. Jangan pernah mendakwaku sebagai lelaki busuk yang rakus melahap rasa sayangmu. Aku tak pernah mencoba merampok tiap kesempatan dalam kesempitan. Berilah maklum pada diriku. Aku dan kau manusia, penuh alpa. Berilah aku setitik kepercayaan. Toh, janjiku tak tergoyahkan dan bisa kubuktikan ribuan kali. Jangan anggap ini semacam rayuan penghias dosaku. Ini hanya serupa penyadaran bahwa kita tak benar-benar harus menanggung hal yang terjadi. Semua telah berlaku, maka biarlah berlalu. Kalau pun itu kau sesali, ijinkan aku yang menanggung setiap cela sepenuhnya. Aku hanya tak ingin kau meratap dalam sedih. Segalanya demi agar kita memiliki banyak alasan lagi untuk kembali berkata-kata, mengungkapkan rasa, atau hal-hal lainnya. Karena itu, hari ini aku menantimu untuk segera berkemas dari bayang-bayang malam. Mari kita kembali menikmati hidup sebagaimana mestinya. Dan aku akan selalu menantimu di tempat yang sama, selalu seperti sedia kala. Ok.
Hari ini aku ingin menjumpai seseorang, berkata-kata, mengungkapkan sebuah penyesalan, sekadar rasa bersalah, atau mungkin apa saja. Namun, mengapa tiba-tiba aku serasa kehilangan setiap alasan untuk setiap tindakan. Serupa malam yang kian sunyi dan dingin. Aku menggigil. Tercerabut dari sesuatu yang tak bernama, tak berasa, tak bentuk, namun mengada. Lalu di mana kau, tempat aku berkisah. Tatapku tak mampu menemukanmu dalam rerimbun kabut. Aku harus mengucap banyak pengakuan hari ini. Tak mampu lagi kubendung. Sungguh. Maafku untuk setiap sisi gelapku, karena kita tak pernah benar-benar menginginkan semua itu terjadi. Pun diriku sendiri, itu benar. Angin yang mengirimkannya tiba-tiba, tanpa sepengetahuan siapa pun. Terlebih diriku. Jangan pernah mendakwaku sebagai lelaki busuk yang rakus melahap rasa sayangmu. Aku tak pernah mencoba merampok tiap kesempatan dalam kesempitan. Berilah maklum pada diriku. Aku dan kau manusia, penuh alpa. Berilah aku setitik kepercayaan. Toh, janjiku tak tergoyahkan dan bisa kubuktikan ribuan kali. Jangan anggap ini semacam rayuan penghias dosaku. Ini hanya serupa penyadaran bahwa kita tak benar-benar harus menanggung hal yang terjadi. Semua telah berlaku, maka biarlah berlalu. Kalau pun itu kau sesali, ijinkan aku yang menanggung setiap cela sepenuhnya. Aku hanya tak ingin kau meratap dalam sedih. Segalanya demi agar kita memiliki banyak alasan lagi untuk kembali berkata-kata, mengungkapkan rasa, atau hal-hal lainnya. Karena itu, hari ini aku menantimu untuk segera berkemas dari bayang-bayang malam. Mari kita kembali menikmati hidup sebagaimana mestinya. Dan aku akan selalu menantimu di tempat yang sama, selalu seperti sedia kala. Ok.Bandung, 230806
Seorang Perempuan di Ujung Beranda

Malam ini ia kembali mengulangi kebodohan yang sama. Kebodohan yang telah dilakukannya dan akan terus dilakukannya selama sesuatu yang ia nanti belum juga kembali. Matanya menembus kebisuan malam. Sementara langit kian larut dalam kegelapan. Udara dingin terasa menyergap. Ia dekap tubuhnya sendiri erat-erat. Perasaannya kembali menerawang menuju entah. Hati kecilnya merasa telah lama merindukan sesuatu. Sejenak ia kembali bimbang. Namun segenap kekuatan kembali ia kumpulkan.
“Mugkinkah ia kembali?” ucapnya pada dirinya sendiri. Angin berhembus lirih menjawabnya.
Selama ini ia sadar bahwa penantiannya itu hanya akan menenggelamkannya akan sesuatu yang sia-sia. Namun sebuah impian selalu membawanya kembali dalam lautan kenangan. Suatu masa ketika ia masih merasakan segalanya. Perasaan yang menuntunnya ke suatu taman penuh bunga. Dan ia merasa teramat nyaman di sana. Di samping pelukan seorang laki-laki berwajah sayu sambil sesekali menatap langit malam yang bertahta di kedua bulatan hitam matanya. Berharap menemukan secercah bintang yang berpendaran. Dan itu, pastilah diperuntukan untuk dirinya. Ya, hanya untuk dirinya seorang. Ah, telah lama semua itu berlalu. Telah begitu lama. Entah. Ia tak lagi sempat mengingat-ingat waktu. Penantian dan harapan telah menenggelamkannya dalam sebuah lautan ketidakmengertian yang hampa. Lagipula, ia tak pernah mampu untuk mengerti mengapa semua itu akhirnya bisa lenyap ditelan segenap ketidakpastian.
Kabut kian pekat membalut angin yang berhembus. Juga seakan turut membalut hati rapuh yang kini dihempas galau. Batinnya kini semakin didera keengganan untuk kembali mempertanyakan segala sesuatunya. Pernah ia mencoba menumpuk–numpuk daftar pertanyaan dan senantiasa berharap bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu suatu ketika akan datang dan menentramkan kerisauan hatinya selama ini. Dan yang ia temui pada akhirnya hanyalah ketiadaan. Kesadaran membawanya kembali pada sebuah realita bahwa sesuatu yang telah pergi tak mesti akan selalu kembali. Walau begitu, ia masih selalu saja memaksakan diri dan berpura-pura memiliki kemampuan yang lebih untuk menanti dan berharap.
Aroma mendung tiba-tiba menghadang lamunannya. Kini ia sama sekali tak mengharapkan hujan karena sayatan dingin hanya akan menjemput kenangan lamanya untuk singgah dan itu artinya akan pula menambah segenap kerisauannya saat ini.
Ia mencoba melangkahkan kaki. Beranjak dari beranda dengan rasa dingin yang mengalir kian pekat. Akan tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Kembali dipandanginya deretan pintu pagar dan berharap bahwa tadi ia telah melihat sesosok tubuh laki-laki di sana. Namun, akhirnya yang ia dapatkan ialah kekecewaan, tak ada siapapun di sana.
“Mungkin aku terlalu banyak mengingat sesuatu yang tak seharusnya kuingat”.
Tanpa disadarinya, dua buah pasang mata mengintai di balik pintu. Dua sosok gadis kecil memperhatikan perempuan yang berdiri ditepi beranda itu. Mereka berbisik-bisik lirih. Namun, tak lama kemudian mereka pun menyingkir dari balik pintu. Sementara perempuan itu tetap mematung di tepi beranda. Menyapu pandangan dalam kegelapan langit malam yang kian sempurna. Tetap saja tak ada yang bisa ia mengerti. Penantian itu telah bertahun-tahun ia jalani, namun tak juga ia temukan jawabnya. Ia hanya seorang perempuan yang merasa tersia-siakan. Laki-laki itu pergi suatu ketika dengan membawa separuh jiwa yang selama ini telah ia bina. Sempat pula ia tersungkur dalam penderitaan yang meraja. Hingga suatu waktu kedua orang tuanya yang merasa iba dengan itu semua memberikan untuknya seorang pengganti yang diharapkan bisa mengobati luka dan penantian akan laki-laki yang telah pergi itu.
Tapi, semua itu tak juga meluluhkan harapannya untuk kembali menatap sosok lelaki yang telah pergi itu. Walau bagaimanapun ia masih ingat, dan akan terus mengingat janji laki-laki itu untuk kembali padanya.
“Dengarlah baik-baik perempuanku, aku akan pergi sejenak, tapi ingatlah, ketika musim telah beranjak hujan, ketika purnama telah bergulir untuk yang keseribu kalinya, aku akan datang kembali padamu.”
Itulah yang terakhir kali ia ingat dari laki-lakinya. Dan sungguh, hal itu membuatnya tersungkur dalam sebuah penantian yang akut. Selama berpuluh tahun. Di tempat yang sama, di ujung beranda.
some teks is missing
Ketika Malam

Malam berselimut kabut dan dingin. Kecemasan dan rasa takut menyelinap di lorong-lorong hati Santo. Dahinya tampak berpeluh. Bahkan, sekujur tubuhnya seakan basah oleh keringat yang mengucur deras. Namun, penderitaan hidup yang ditanggungnya selama ini ternyata lebih kuat memaksanya untuk terus melangkah mendekati rumah megah itu.
“Jangan lakukan Santo, mencuri itu perbuatan yang dikutuk Tuhan,” kata-kata istrinya itu masih saja terngiang-ngiang di telinganya.
“Tuhan? Huh, sejak kapan Tuhan perduli pada kita? Selama ini kita selalu percaya pada-Nya, memuja-Nya, mengikuti setiap perintah-Nya, tetapi lihat, balasan apa yang Ia berikan pada kita! Kekayaankah? Tidak, Surti! Tuhan tidak pernah peduli pada kita. Lalu untuk apa kita juga harus peduli padanya?”
“Tak sepantasnya kau berkata begitu! Tuhan selalu perduli pada kita. Bersyukurlah bahwa Ia masih memberi kita kehidupan. Kemelaratan ini hanya setetes ujian bagi keimanan kita.”
“Persetan dengan Tuhan dan ujian-Nya. Aku hanya tak ingin lagi hidup melarat. Titik!”
“Tapi, Santo…”
“Mengertilah sedikit Surti. Pekerjaanku sebagai buruh tak pernah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kulakukan ini demi kelangsungan hidup kita selanjutnya. Hutang kita telah cukup banyak. Apakah kau tidak merasa malu ketika si Romlah itu tidak mengijinkan kau lagi untuk menghutang di warungnya. Lihatlah ketiga anak kita, Si Sulung, ia berapa kali ditegur oleh gurunya karena sudah beberapa bulan ia menunggak uang SPP. Belum lagi Si Jaka yang harus berjualan koran untuk membantu meringankan biaya hidup kita. Lalu untuk susu Si Kecil ini, kita harus dapat duit dari mana? Ah, sudahlah, Risman sudah menungguku di warung ujung gang sana. Malam ini sudah kuputuskan untuk ikut dengannya.”
Santo pun beranjak dari rumahnya diiringi dengan teriakan-teriakan istrinya yang memanggil-manggilnya untuk kembali. Namun Santo tidak lagi menghiraukannya. Hatinya telah teguh, segenap niat pun telah ia bulatkan untuk ikut Risman merampok salah satu rumah mewah di kompleks perumahan elit itu tengah malam nanti. Di kejauhan, Surti, istrinya, kecewa karena ia lupa bercerita tentang mimpi buruknya beberapa hari yang lalu. Mungkin semacam pertanda atau firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tetapi ia masih belum mampu memastikannya. Sementara langit tampak mendung dan angin yang mengantarkan rasa dingin berdesir halus. Santo dengan terburu-buru berjalan menuju warung remang-remang di ujung gang. Risman yang telah menunggu, kemudian segera menyambut kedatangannya.
“Akhirnya kau datang juga Santo. Kedatanganmu ini menandakan keberanianmu untuk aksi kita malam ini. Apakah kau sudah siap?”
Santo terdiam dalam bimbang. Kepalanya menunduk. Namun, ia ingat bahwa SPP Si Sulung harus secepatnya dibayar, ia iba pada Si Jaka yang berjalan di tengah terik mentari untuk menjajakan koran dan majalah, ia ingat Si Kecil yang selalu merengek minta disusui tapi payudara istrinya tak mampu lagi mengeluarkan ASI, dan ia juga ingat warung di depan rumahnya tidak lagi mau untuk memberinya hutang untuk keperluan rumah tangganya. Bayangan itu membuat tekad Santo bangkit kembali. Ia tidak mau lagi hidup terpuruk dalam jurang kemiskinan
“Ya, aku siap Risman,” ucapnya tegas.
Risman menatapnya tajam. Risman tahu bahwa masih ada gurat-gurat kebimbangan di wajah Santo. Bagaimanapun ini adalah untuk pertama kalinya Santo melakukan perampokan. Sementara Risman sendiri sudah berpengalaman dalam hal ini. Bahkan, ia pernah beberapa kali masuk penjara karenanya. Sesungguhnya Risman pun enggan untuk mengajak Santo melakukan perampokan ini. Apalagi, Santo tidak punya pengalaman sedikitpun dalam hal kejahatan. Akan tetapi, Santo mendesaknya agar menyertakan dirinya dengan berbagai alasan. Akhirnya, Risman pun terpaksa membawa Santo dalam aksi perampokan kali ini.
“Ingatlah Santo, apa yang akan kita lakukan ini penuh dengan resiko. Jika kita bernasib sial, mungkin intimidasi aparat sudah menunggu kita di balik jeruji besi. Bahkan bisa lebih parah lagi, kematian akan menimpamu. Teguhkan hatimu dari sekarang. Pekerjaan kita ini terlarang bagi keragu-raguan. Jika sedikit saja ada kebimbangan di hatimu, lebih baik mundur saat ini juga karena keraguan adalah awal kegagalan kita.”
“Sudahlah Risman, kita sudah bicarakan hal ini berulang kali. Akupun telah mengerti. Itulah sebabnya aku berani datang karena lebih besar tekadku untuk segera lepas dari kemelaratan. Sesungguhnya merekapun tak kurang bajingan daripada kita, bukan? Harta yang mereka dapatkan adalah hasil praktik culas dan memeras rakyat jelata. Hanya saja cara yang mereka gunakan lebih rapi dan licik. Merekalah yang membuat kita semua terpaksa terus-menerus merasakan hidup yang keparat. Mereka akan menerima pembalasannya malam ini.”
Risman pun tertegun dengan tekad Santo. Ia mengangguk pelan.
“Baik. Apakah kau sudah siapkan peralatannya?”
“Lengkap.”
“Bagus. Kita segera beranjak.”
Santo kembali menepiskan kebimbangannya. Kemudian dipandanginya Risman dan beberapa kawan lain yang juga ia kenal. Ia mencari-cari, namun tak jua ia temukan kebimbangan semacam yang dirasanya. Terbawa suasana yang lainnya, maka ia semakin menguatkan kembali hatinya, dan kian terbawalah ia pada gairah nafsu untuk menjarah kekayaan. Kemudian dengan komando Risman, setelah meyakinkan segala persiapan telah sesuai rencana, bergegaslah mereka menuju sasaran.
Malam menjelang kian larut. Rerimbun pohon bergoyang dengan penuh irama kecemasan. Tak dirasa, mereka kini telah tiba di bagian samping rumah megah yang dituju. Pagarnya menjulang setinggi lima meter dengan besi-besi runcing di ujungnya. Risman kemudian memberi isyarat pada Santo untuk bersiap siaga, juga untuk terus waspada. Itu semacam aba-aba bahwa mereka akan mulai berkerja.
Continued
MEMBURU KADO CAHAYA

“Aku tak ingin sesuatu yang muluk-muluk. Hanya sekuntum cahaya sebagai kado ulang tahunku,” ucapnya suatu ketika di hari ulang tahunnya.
“Ya, tapi di mana aku bisa dapatkan sekuntum cahaya, Nona.”
“Lho, itu terserah padamu. Aku tidak mau tahu, yang penting kau harus bisa mendapatkan sekuntum cahaya untukku,” pintanya, “tidak banyak kan? Hanya sekuntum cahaya. Selain itu tidak! Cepatlah! Aku tidak mau terlalu lama menanti.”
O, Sang kekasihku tercinta. Pintamu itu ada-ada saja. Di mana lagi aku bisa mendapatkan sekuntum cahaya jika dunia yang kita huni ini hanya penuh dengan kegelapan yang meraja. Melingkupi kehidupan kita yang kotor. Penuh kemunafikan dan durjana. Lihatlah! Aku punya segalanya, harta yang berlimpah, emas permata, kedudukan, juga jabatan tertinggi. Apapun yang kau minta pasti akan kuberi detik ini pula, asalkan selain cahaya itu.
Ribuan tahun yang lalu, mungkin kita akan mudah mendapatkan sekuntum cahaya. Mereka banyak berceceran di toko-toko buku, rumah peribadatan, di rumah–rumah, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan, hampir setiap orang di negeri kita ini memiliki sekuntum cahaya. Akan tetapi, kini semua itu hilang tiba-tiba, semenjak kejujuran sudah tidak ada lagi, dusta dan kemunafikan merajalela di mana-mana. Hingga sekuntum cahaya pun tersingkirkan. Tempat mereka tergantikan nafsu dan keserakahan yang menakutkan. Dunia kita pada akhirnya hanya penuh dengan kekacauan. Tetapi justru di sanalah kita bisa hidup dan berkuasa. Mengendalikan orang-orang yang lemah dan malas. Lalu kini, di saat sekuntum cahaya sudah tidak ada lagi di mana pun, tiba-tiba kau mengharapkannya kembali. Untuk apa semua itu, Nona? Bukankah nafsu dan kegelapan itu lebih menguntungkan untuk kita. Kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan apa pun yang kita inginkan. Harta, jabatan, emas permata, dan semua yang kita ingini.
“Untuk apa katamu? Justru karena barang itu langka, maka akan semakin istimewa nilainya. Apalagi berumur ribuan tahun. Bayangkan jika kita bisa mendapatkannya. Pasti kita akan dikenal di seluruh semesta karena berhasil menemukan sesuatu yang telah menghilang selama ribuan tahun. Lagi pula, masa sih kamu tidak bisa mendapatkannya. Kamu ialah orang terpandang dan berkedudukan paling tinggi di negeri ini. Bukankah kau tinggal memerintahkan ribuan bawahanmu itu untuk melaksanakannya. Sementara kau sendiri tidak perlu turun tangan lagi. Para anak buahmu itu pasti akan membereskan semuanya. Mencari ke segenap penjuru mata angin untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian kau tinggal membingkiskannya untukku. Setelah itu, barulah kau bisa memiliki aku sepenuhnya. Aku janji. Setelah kau bisa mendapatkan sekuntum cahaya itu, maka apapun yang kau mau dari aku akan kuberikan sepenuh hati. Hei, kau dengar tidak? Itu bukan perkara sulit, bukan?”
Ah, akhirnya kuturuti juga permintaan kekasih tersayangku itu. Bagaimanapun ia adalah satu-satunya orang yang aku cintai. Walaupun sebenarnya dengan kedudukan dan kekuasaanku, akan mudah kiranya mendapatkan perempuan mana pun yang aku suka. Berapa banyak perempuan pun yang aku kehendaki. Secantik dan semolek apapun itu. Namun perempuan ini mempunyai keistimewaan yang tak dipunyai perempuan lain. Ia mampu membuatku bertekuk lutut di hadapannya. Memujanya, menuruti semua keinginannya, mematuhi perintahnya, menyetujui sarannya, dan masih banyak lagi. Entah, mengapa aku tidak pernah mampu untuk membantah. Seolah-olah, kata-katanya adalah semacam sabda Tuhan yang tak bisa kulanggar.
Kukerahkan seluruh bawahanku: para tentara, karyawan, pejabat, pekerja, hingga masyarakat dan dari mulai anak-anak sampai tua renta. Hampir seluruh orang yang ada di negeri ini membantuku untuk menelusuri keberadaan cahaya. Para tentara menggeledahi seluruh rumah di negeri ini, mendeteksi keberadaan sekuntum cahaya. Para pegawai mensensus peduduk dengan harapan akan menemukan sekuntum cahaya. Seluruh jengkal daratan, semua tetes lautan telah mereka gali, angkasa pun telah pula mereka jelajahi. Namun, belum juga mereka temukan apa yang aku cari. Sementara kekasihku kian resah menunggu.
“Masa sih begitu saja tidak becus. Aku sudah merasa bosan menungu. Aku hanya ingin bahagia. Bukankah sebelumnya kau berjanji untuk membahagiakan aku dengan menuruti semua keinginanku. Dan selama ini, bukankah aku tidak banyak meminta kepadamu. Mengapa ketika aku meminta untuk pertama kalinya kau tak mampu memberikanya kepadaku. Hanya satu saja, sekuntum cahaya, tak banyak kan?”
“Ya, tapi….”
“Jangan berdalih! Kau adalah penguasa tunggal di negeri ini. Apa sih yang tak bisa kau lakukan. Semua orang di negeri ini pasti akan menuruti setiap perintahmu. Carikan aku sekuntum cahaya. Titik.”
Cahaya, Oh cahaya di manakah engkau berada, sang kekasihku menginginkan engkau sebagai hadiah ulang tahunnya. Sementara telah ribuan tahun engkau menghilang tak tentu rimbanya. Kemanakah aku harus mencarimu? Duhai cahaya, aku hanya ingin sang kekasihku itu bahagia. Dan sebagai syarat kebahagiaannya itu, ia menginginkan engkau di hari ulang tahunnya? Apa yang harus aku lakukan jika segala cara telah aku tempuh namun tak jua kudapatkan kau.
Next teksis missing
17 August 2006
Hidup
 Hidup kian entah, sekadar rutinitas yang tak pernah bisa kunikmati. Cuaca semakin membeku, malam begitu senyap, dan aku tak kunjung juga mengerti mengapa waktu bergulir teramat cepat. Padahal telah kuatur jam waktu agar berputar lambat-lambat. Serupa angin yang tak pernah mampu kutelusuri perwujudannya. Seperti air yang tak pernah berbentuk, tak terjamah, lihai menyelusup celah-celah. Hidup juga senantiasa menuntut lebih dari yang kita punya, merampas lebih dari yang kita miliki, membajak lebih dari yang kita persiapkan. Rakus yang tak terpuaskan hingga kita kehilangan setiap keinginan, juga harapan.
Hidup kian entah, sekadar rutinitas yang tak pernah bisa kunikmati. Cuaca semakin membeku, malam begitu senyap, dan aku tak kunjung juga mengerti mengapa waktu bergulir teramat cepat. Padahal telah kuatur jam waktu agar berputar lambat-lambat. Serupa angin yang tak pernah mampu kutelusuri perwujudannya. Seperti air yang tak pernah berbentuk, tak terjamah, lihai menyelusup celah-celah. Hidup juga senantiasa menuntut lebih dari yang kita punya, merampas lebih dari yang kita miliki, membajak lebih dari yang kita persiapkan. Rakus yang tak terpuaskan hingga kita kehilangan setiap keinginan, juga harapan.Namun, hidup dengan timbunan persoalan ialah sebuah keniscayaan. Siapa yang mampu mengelak? Mengutuki hidup ialah sebuah kesia-siaan. Jalan keluar adalah jawabnya.
Namun, aku membenci dusta sebagaimana membenci kejujuran yang menyakitkan. Tak mudah menerima setiap kenyataan ketika ia bertentangan dengan setiap keinginan. Ribuan kekhwatiran tak pernah henti berkembang biak. Memamah setiap kehendak. Aku muak. Sungguh, teramat muak. Maka maafkanlah aku, ijinkan aku menjadi orang yang memerdekakan diri. Lepas dari tuntutan dan setiap keharusan. Aku ingin berkehendak dan memutuskan tanpa harus mempertimbangkan.
Bandung, 05
Seorang Perempuan Suatu Ketika

Aku melihat kesuraman seorang perempuan pada tengah malam buta. Airmata bagai hujan yang menderas. Bintang dan kegelapan malam menjadi saksi yang membeku. Ia adalah seorang yang menyesali diri. Dan entah bagaimana, ia mampu mengubah kesedihan menjadi kelegaan. Aku adalah seorang pendengar yang baik. Selalu. Penyesalan ialah sia-sia, karena waktu tak mampu berbalik arah. Dan maafkanlah aku, mungkin juga salahku yang terlalu terbuka.
Untuk sementara aku dihempas bimbang. Ada hal-hal yang sering tak bisa kupahami. Kenangan itu apa? Mengapa ia selalu saja menjelma belenggu yang memenjarakan. Lalu aku harus bagaimana lagi? Jika tak ada seorang pun yang mampu. Moga suatu saat seseorang akan mengerti, bahwa terlalu bodoh baginya untuk terus larut dalam persoalan remeh semacam itu. Sesuatu yang telah kita jalani harus mengalah untuk tertinggal dan berlalu, sebab hidup masih panjang membentang.
Bandung, 220506.
Kita Pernah Berbagi Hujan
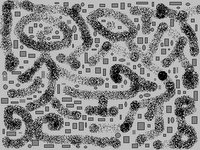
I
Kita pernah berbagi hujan pada suatu malam. Selepas mendengar bait-bait puisi yang disuarakan dengan lantang. Kau terlalu memaksakan kehendak waktu itu. Seakan merasa diri lebih mampu menantang badai sekalipun. Dan aku harus bersetia melindungimu dari cercaan cuaca, juga tikaman dingin. Kita lalu bercakap-cakap tentang kecemasan. Sisa-sisa tawa berderai untuk selanjutnya tersaingi muram dan kegalauan. Dan akhirnya aku tahu, kau bukanlah seorang perempuan yang senantiasa mengangguk. Karena setiap kata-kataku dimentahkan keegoisan yang merasa diri lebih dari siapa pun. Aku menunduk di antara angan yang basah. Perjalanan kita dipenuhi tatap mata yang sendu dan senyuman-senyuman yang tak pernah mampu kutelusuri maknanya. Aku kembali harus mengalah. Pulang dengan sisa-sisa kelemahan seorang laki-laki yang pemurung. Namun, kata dan doa yang kau sematkan terakhir kali telah membuatku kembali tersentuh oleh kepasrahan, untuk kembali bersimpuh dalam tatap matamu yang purnama.
II
Aku harus kembali berani bertaruh. Mencoba memahami sesosok perempuan untuk yang kesekian kali. Seseorang yang selalu terbangun pada sepertiga malam yang usai. perempuan yang selalu mengulum diam dan senyuman, juga keteduhan yang muram. Tapi akhirnya aku mengerti, ia menyimpan sejenis kepura-puraan yang akut. Berselimut sikap dan setumpuk pertanyaan yang tak pernah mampu kuterjemahkan seketika. Serupa labirin teka-teki.
Kini, aku menjelma sesosok pemain di atas panggung, bersiap dengan peran dan naskah tak berwujud. Ah, aku memang seorang laki-laki yang pandai menerka setiap peristiwa.
Bandung, 050305
Aku dan Kita
 Sebentang perjalanan sulit telah aku tuntaskan, mengajariku hal-hal asing tentang kebersamaan, tantangan, keputusan, juga pengabdian. Sungguh, aku lelah dalam sisa-sisa ketidakberdayaanku. Hari-hari semakin larut di antara bayang kecemasan masa depan. Aku kian terdesak. Penantian ini tak juga kunjung terselesaikan. Berapa lama lagi aku harus menungggu?
Sebentang perjalanan sulit telah aku tuntaskan, mengajariku hal-hal asing tentang kebersamaan, tantangan, keputusan, juga pengabdian. Sungguh, aku lelah dalam sisa-sisa ketidakberdayaanku. Hari-hari semakin larut di antara bayang kecemasan masa depan. Aku kian terdesak. Penantian ini tak juga kunjung terselesaikan. Berapa lama lagi aku harus menungggu?Sempat kutinggal, entah untuk berapa lama. Tak sanggup lagi menghitung waktu yang berlalu. Musim berganti, namun selalu ada yang tetap tinggal. Sebagaimana juga selalu ada yang pergi dan datang. Mungkin aku tak lagi mesti belajar memilih atau dipilih. Seseorang mesti berpasrah pada kenyataan. Ada hal-hal yang tak bisa kudapatkan darinya. Sebagaimana ada hal-hal yang tak bisa ia dapatkan dariku. Segala sesuatu akan tiba pada tempatnya masing-masing. Walau begitu, aku ingin segalanya tak mesti berbalik arah. Selalu ada proses dan fase untuk berubah. Kuingin segalanya mengalir serupa hujan. Sementara masih banyak kewajiban yang mesti kupenuhi. Dan kemarau belum juga reda. Bayang-bayangnya masih banyak tertinggal di jendela.
Tak ada lagi kata kepastian di mana pun. Hidup selalu bergelut dengan kemungkinan yang tak terduga. Bahkan, kadang penuh puing-puing menyesakkan. Sebelumnya, telah kita tuntaskan kegalauan ini. Sebab riuh angin telah lama mengirimkan duri-duri kekhawatiran di dadaku. Kita kikis habis sudah segala pertanyaan yang mengendap. Belajarlah bersikap dan jujur pada kehendak. Bukankah aku telah cukup mengajarimu berbagai macam kejujuran? Ah, sepertinya tidak! Kita adalah orang-orang yang berbeda. Selalu saja memperdebatkan rasa yang selalu terlalu sulit ditafsirkan.
Bandung, 070605
Pulang

I
Mungkin aku mesti memetakan kembali rencana-rencana, juga berbagai kemungkinan yang ada. Telah banyak kuhabiskan segala yang kupunyai. Lagi pula keduniawian ini untuk apa? Bayang yang ingin kugapai semakin mengabur. Telah lama aku terbenam dalam kekhawatiran ini. Berbaur bersama keterasingan rasa. Selamat malam, Kabut. Segalanya menguap dalam alunan semu. Ada sembilu yang menusuk. Namun, tak lama lagi aku akan pergi. Menuju gelombang kenangan dan riuh masa lalu. Tunggulah, Malam. Aku akan pulang.
II
Tentu tak setiap orang punya tempat di mana ia bisa kembali pulang. Maka bersyukurlah siapapun yang bisa merasakan makna kepulangan. Mengunjungi masa kecil yang tertinggal, tempat di mana kita belajar untuk meraba hidup dengan segala keluguannya. Maka di sinilah aku untuk kembali pulang. Mengunjungi orang-orang yang telah banyak mengajariku tentang hidup, juga dunia. Ada kebersamaan yang mengharukan, juga keterasingan suasana. Ah, mungkin sudah waktunya bagiku untuk kembali belajar mengenal.
III
Tak bisa kuingkari, ada banyak ingatan yang tercecer di sini, di setiap tempat-tempat tak bernama, di setiap tumpukan benda-benda, di setiap wajah-wajah, juga di setiap bayang-bayang peristiwa. Kadang aku menemui salah satunya, tapi juga kadang kehilangan yang lainnya. Aku harus belajar untuk terus bersengketa dengan keinginan yang tak bisa kunjung kumengerti. Namun, siapakah aku, sementara kepulangan juga berarti jerat pengabdian. Aku sering merasa harus kembali menjelma kanak-kanak di sini.
Bandung, 10-230605
Hilang
 Aku kehilangan sesuatu. Tak cukup waktu untuk mencari. Karena tahu, tak akan kutemukan di mana pun. Kemanakah sesuatu itu pergi? Bahkan sang angin pun tak sanggup mengirimkan kabarnya padaku. Entah, akhir-akhir ini aku semakin merasa kehilangan. Sungguh, pencarian yang sia-sia.
Aku kehilangan sesuatu. Tak cukup waktu untuk mencari. Karena tahu, tak akan kutemukan di mana pun. Kemanakah sesuatu itu pergi? Bahkan sang angin pun tak sanggup mengirimkan kabarnya padaku. Entah, akhir-akhir ini aku semakin merasa kehilangan. Sungguh, pencarian yang sia-sia.Namun aku telah menduga, prasangka yang menjebakku pada sebuah kenyataan yang menyesakkan. Inilah waktu di mana aku harus menenangkan diri sendiri. Tapi hidup masih terus bergulir. Dan aku telah memamah banyak peristiwa, juga kata-kata. Menyadari bahwa hidup hanya sebuah kesementaraan. Tak ada yang sepenuh hati abadi. Kita selalu tiba pada saat di mana ada orang-orang yang saling membutuhkan untuk peduli. Hanya dalam suatu kurun waktu tertentu. Selebihnya tidak lagi. Tak ada yang kekal milik kita, pun untuk hidup itu sendiri. Belajarlah arti perpisahan sebelum memulai sebuah pertemuan. Pahamilah makna luka ketika akan tertawa. Bersyukurlah, beban dan segala yang memupuk kini telah sirna. Walau untuk sesaat, selalu ada ruang-ruang kosong yang tertinggal, semacam belatung-belatung di sisa sarapan pagi kita hari kemarin. Kau tidak sendiri, Sobat. Aku pun telah banyak kehilangan. Mulailah mencintai tanpa takut kehilangan.
Bandung, 230805
Kita dalam Sebuah Percakapan
Ia datang bersama malam. Pada suatu ketika. Waktu itu musim belum beranjak bosan dari kecemasannya. Dan aku merasakan kegelisahan yang tiba-tiba. Rasanya bagai menopang seluruh beban semesta di bahuku. Tapi tatap matanya memancarkan keceriaan sebuah permainan. Bermanja serupa bocah gadis yang memohon sebuah boneka Barbie untuk kado ulang tahunnya. Lama memang kami tak jumpa. Masing-masing harus membenamkan diri pada kesibukan yang di luar batas kewajaran. Ini mungkin sekadar jeda, sebuah liburan singkat. Dan ia tanpa ragu menyerbuku, berharap melepas setumpuk kerinduan yang telah hampir meledak di dadanya.
Maka bermanja-rialah sikapnya padaku. Kemesraan yang tak mampu terbendung. Kami habiskan waktu dengan masa bersama sepenuhnya. Serasa tak ada lagi waktu, karena dunia mungkin akan luluh lantak di esok hari. Dan hal yang paling indah baginya selalu, adalah memandang langit malam yang penuh tebaran bintang. Saat itu, kami akan luangkan waktu sejenak. Menghamparkan diri pada sebuah taman lapang untuk kemudian duduk atau berbaring menengadah. Mengagumi keindahan langit malam tanpa berdecak. Hanya sesekali kami berbincang, selebihnya adalah menyimpan tatap dan angan pada suatu ruang yang entah di mana.
Namun kali ini, aku merasa tak biasa. Resah yang selama ini menebar benih, telah menyubur, belukarnya terasa amat menyesakkan. Aku mengerti. Kami tak selamanya bisa bersama. Ini hanyalah sebuah kefanaan. Sesuatu yang akan pupus dihantam putaran waktu. Dan kami telah begitu saling mengerti. Menunggu satu sama lain untuk bersiap, berkemas, untuk kemudian menghilang. Mungkin inilah waktu itu. Dan sebagaimana perkiraanku, dialah yang akan melenyapkan diri terlebih dahulu.
Ia melamarku kemarin malam, ucapnya di sela waktu.
“Sungguh.”
Ya, awalnya sih aku kira bercanda, tapi sepertinya serius.
“Aku ngak tahu harus bilang apa. Kebanyakan perempuan akan bahagia bila dilamar. Selamat! Aku turut bahagia untukmu.”
Sungguh?
“Tentu saja.”
Ia menanggapinya dengan diam. Tiba-tiba aku menghirup nafas mendung di wajahnya.
“Kenapa? Ada masalah?”
Aku sedih.
“Ya, kelihatan di muka kamu.”
Aku harus bagaimana? tanyanya sunggguh-sunggguh.
“Secara harfiah, kalian seharusnya sudah sama-sama siap. Masalahnya, mungkin secara psikologis kamu masih bimbang. Tapi kamu sendiri telah tahu jawabannya. Banyak hal yang tak perlu dipertimbangkan, kamu hanya perlu melakukan.”
Sulit rasanya membayangkan harus memasrahkan segenap raga, juga sukma pada laki-laki yang tidak kucintai.
“Kamu berhak memilih. Tapi aku ragu kamu bisa. Pahamilah dari kini. Inilah kepatutan hidup. Setiap pilihan menyimpan setiap kemungkinan, juga kesulitan-kesulitan. Namun, ketika kau telah memutuskan, tak ada waktu lagi untuk membantah. Segalanya mesti kau terima dengan tabah. Yakinlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang penyabar. Dan kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang mulai belajar mencintai setelah mereka bersama. Aku yakin kamu bisa. Biarlah waktu yang nanti akan membantumu. Usailah meresahkan diri sendiri, suatu ketika akan kau temukan jawabannya.”
Hanya satu yang kini kupikirkan, katanya tiba-tiba.
“Apa?”
Kamu.
“Lho, kenapa dengan aku?”
Aku masih menginginkan kamu.
Kata-katanya menyimpan kesungguhan yang sempurna. Pandangannya menyergapku dengan lekat. Tapi kini aku telah begitu terbiasa dengan permohonan semacam ini. Telah lama, terlalu lama. Kami selalu memperdebatkan hal yang sama. Namun, tak juga kunjung kami mengerti segala yang terjadi.
“Kita sudah bicara banyak tentang ini. Hadapilah kenyataan. Sudah tak ada takdir untuk kita. Aku hanya persinggahan sejenak.”
Kenapa aku tak bisa memiliki orang yang aku cintai? tanyanya kembali dengan lantang.
“Kenyataannya bahwa sebagian besar perempuan tampaknya tidak terlalu membutuhkan laki-laki yang dia cintai, sebaliknya ia lebih perlu laki-laki yang mencintanya. Suatu saat kamu akan sadari itu.”
Sepertinya ia tak terlalu puas dengan sebuah jawaban. Kembali ditatapnya mataku lekat dan erat. Dahinya berkerut. Sebuah tanda bahwa ia berpikir banyak-banyak. Dan pertanyaan yang ia lontarkan kemudian begitu pekat dengan rasa curiga.
Katakan! Apakah kau juga menginginkanku sebagaimana aku menginginkanmu?
“Sejujurnya,” ucapku dengan mencoba mengais setiap kemungkinan untuk sebuah jawaban yang terbaik, “aku pernah menginginkanmu.”
Pernah?
“Ya, pernah. Tapi kita sama-sama tahu. Impian itu kandas sejak .... Ah, mungkin kita tak perlu mengungkit masa lalu. Untuk kemudian hanya akan mengungkap kenangan buruk. Lalu berdebat tentang penyesalan, cinta, juga airmata. Dan kita, kemudian akan kembali berputar-putar di tempat yang sama.”
Apakah kini kau tidak lagi mencintaiku?
“Tentu tidak mudah melupakan cinta. Aku masih mengasihimu. Itu benar. Tapi kita telah sama-sama mengerti kesulitan yang kita hadapi. Pengalaman hidup mengajarkan aku untuk berlaku bijak dan tabah. Setelah banyak aku kehilangan sesuatu. Bahkan untuk yang paling pedih sekalipun. Kini, kita mesti banyak belajar untuk mencintai tanpa takut kehilangan.”
Tapi aku tak ingin kehilangan kamu. Aku ingin terus mencintaimu. Aku ingin tetap memilikimu. Selalu sampai kapanpun.
Perasaannya kian meluap serupa ombak pasang.
“Tentu, aku tak bisa memaksamu untuk berhenti mencintaiku. Hanya hatimu sendiri yang mampu melakukannya. Tapi ada orang lain yang mungkin lebih berhak memilikimu. Seseorang yang dulu telah kau pilih. Tak perduli walau rasa penyesalan itu masih selalu menjeratmu. Aku yakin, waktu bisa mengatasi segalanya, tak terkecuali cinta. Lambat laun aku akan tergantikan, cinta ialah ibarat jamur di musim penghujan. Akan muncul dengan tiba-tiba. Karena itu, bukakanlah hatimu. Belajarlah untuk mencintainya dan kau akan menemukan kasih sejatimu.”
Malam bertambah malam. Aliran dingin menyergap suasana. Menyelusup ke dasar hati yang terdalam. Dan sedikit demi sedikit membangkitkan kekecewaannya akan harapan yang tak berbalas.
Sepertinya kamu senang ya, kalau aku pergi dari kamu? Agar kamu juga bisa pergi ke lain hati, kan?
“Tak baik berburuk sangka. Tentu orang-orang akan yang bersedih jika kehilangan orang terdekatnya, tak terkecuali aku. Demi Tuhan, aku akan sedih kehilanganmu. Kita tak mampu bersama bukan karena sebuah alasan, tetapi lebih karena sebuah keniscayaan. Tak pernah ada sesuatu yang abadi, pun untuk hidup itu sendiri. Segalanya hanya sebuah kesementaraan. Sadarilah arti perpisahan sebelum memulai sebuah pertemuan. Pahamilah makna luka ketika akan tertawa. Karena perpisahan kadang juga menyimpan setumpuk pelajaran dan kebaikan. Suatu saat kau akan mengerti itu, aku yakin.”
Aku tuh nekad banget ya, terlalu memaksakan kehendak, ujarnya kemudian.
“Aku telah mengenalmu jauh dari yang kamu kira. Kamu pemberani, seperti pejuang. Tegar bagai karang, berkobar laksana api. Telah banyak yang kamu hadapi. Dan itu membuatmu belajar untuk terus bertahan tanpa menyerah. Karena menyerah adalah berarti pupus. Tergilas kenyataan yang tak memihak. Hidup mengajarkan kamu untuk memaksakan setiap cara, juga kemungkinan. Aku tak pernah menyalahkan kamu demi alasan semacam itu. Sunggguh, aku sangat bermaklum diri.”
Tak bisakah kamu seperti aku. Mempertahankan apa yang kita rasakan?
“Aku mempertahankan apa yang sebaiknya aku pertahankan. Dan itu telah berlalu sejak kepergianmu waktu itu. Lagi pula, aku tak pernah mengemis apa pun pada siapa pun. Sebab beginilah aku adanya, menerima apa yang berhak aku terima. Dan melepaskan apa yang tak berhak aku pertahankan.”
Kamu pengecut. Kamu tak punya keberanian untuk menentang kenyataan, tuduhnya dengan keras.
Aku menghela nafas. Sekadar menghembuskan keriuhan yang menumpuk di dadaku. Sungguh, betapa aku mencoba memaparkan setiap penjelasan dengan bijak dan seksama. Namun, ketika logika dikalahkan prasangka, maka tak pernah ada penafsiran yang sama. Aku dan dirinya selalu bersimpang pemikiran.
“Sebaliknya,” lanjutku kembali, “aku belajar meneguhkan hati dan mengalahkan setiap ketakutan untuk tetap bersikukuh pada apa yang telah aku yakini. Ketahuilah, aku telah banyak mencoba dan itu sudah cukup bagiku. Aku harus memamah setiap kekhawatiran dan mengingkari kenyataan bahwa aku masih mengasihimu. Dan jalan hidup mengharuskan kita untuk tak lagi memaksakan perasaan. Lagi pula, siapa yang mampu menolak kenyataan, pun tidak untukmu. Kita telah sama-sama tahu itu.”
Tapi ini bukan hal yang kuinginkan. Aku terperangkap. Dan hidup —entah bagaimana caranya— telah memaksaku untuk tak bisa mengelak dari keharusan yang menyebalkan ini.
“Aku paham. Itulah sebabnya aku mencoba untuk selalu terbuka memaafkan setiap kesalahan di masa lalumu. Dan menerimamu untuk bersama walau sesaat, sebelum kau benar-benar pergi. Karena itu, seharusnya kita tak perlu memperdebatkan semuanya. Kita telah cukup lelah dengan itu semua. Kini, sandarkan bebanmu padaku. Aku tahu, kamu begitu penat setelah banyak bergulat dengan keharusan hidup. Menepilah di sini, dalam pelukanku. Ada secangkir kasih yang hangat untukmu.”
Sejenak gundahnya mereda. Aku tak bisa meneruskan persengketaan ini. Semacam lorong-lorong gelap tak bertepi. Di mana hanya kebuntuan yang akan kutemui setelahnya. Mungkin rayuan semacam itu bisa menghilangkan resahnya walau sesaat. Ia pun tersadar sejenak. Kemudian mengibaskan butiran mutiara yang telah mulai berderai dari tatapnya. Perlahan ia sandarkan tubuhnya dalam dekapku. Dan kembali menatap kerlip bintang di lautan malam.
Ah, aku menyesali masa lalu. Kini aku merasa begitu bodoh hingga pernah meninggalkan orang yang begitu kucintai.
“Tak perlu menyesal. Karena kini kita masih bisa bersama. Lupakan apa yang telah dan seharusnya terjadi. Segalanya telah berlalu dan menjadi pelajaran bagi kita. Kini, nikmatilah waktu yang tersisa. Kita curahkan dengan kenangan indah dan ingatan-ingatan yang tak akan terlupakan.”
Aku khawatir kau akan pergi dariku? katanya kembali.
“Tidak, aku akan tetap ada di sini. Mungkin untuk terus mengenangmu. Karena hidup juga menyisakan banyak ingatan yang tak terlupakan. Tapi kita terlarang untuk terus tenggelam di dalamnya. Karena bayang-bayang masa lalu ialah semacam lorong-lorong labirin tak berujung. Sungguh teramat menyesatkan. Sebaliknya, mungkin aku juga perlu untuk memulai hidup baru. Lepas dari jerat rutinitas satu, untuk kemudian terperangkap ke lain rutinitas. Bukankah hidup harus terus dijalani. Dan kita masih punya impian, bukan? Ada banyak cara untuk mewujudkannya. Walau hidup selalu memberikan berbagai macam kemungkinan yang tak terduga. Dan kita akan selalu kalah bila bertaruh tentang apa yang akan terjadi. Tapi setiap kemungkinan menyimpan harapan, pengalaman, dan pelajaran baru tentang hidup itu sendiri.”
Lalu, setelah ini kau akan bersama siapa?
“Jangan khawatir, masih ada banyak orang yang berharap dan menungggu. Aku tidak akan kesepian tanpamu. Tapi tidak dalam waktu dekat, karena untuk saat ini aku harus banyak menenangkan diri. Berbenah dengan perasaan dan pikiran yang telah lama tak beraturan. Tetap doakan aku untuk bahagia, sebagaimana juga aku selalu mendoakanmu.”
Tapi aku tetap tak ingin kita berpisah. Tuh kan, akhirnya aku selalu merasa kalah. Dan kamu selalu membuat aku merasa semakin kalah. Kenapa sih, apa yang aku ingini ngak pernah bisa terjadi, untuk sekali ini saja.
Lembaran kaca kembali berlinang dalam tatapnya.
“Pandailah bersyukur. Mengapa kita selalu lupa dengan semua yang telah diberikan hidup untuk kita, tapi tak pernah lupa segala yang tidak diberikan hidup untuk kita. Aku tahu, telah banyak pedih yang kamu jalani hingga kamu seperti sekarang ini. Ada banyak cobaan, aral, dan rintang. Tentu itu menyakitkan. Puncak tinggi tak berjalan landai, tapi keras dan terjal. Keindahan menanti dipuncaknya. Dan lihatlah sekarang. Telah lahir sesosok yang baru, seseorang perempuan yang setegar karang. Tak perduli walau onak dan duri tertancap di hatinya. Bahkan mampu menahan badai dan hujan sekalipun. Seorang perempuan yang juga memiliki kepercayaan diri setinggi langit dengan semangat berjuang dan pantang menyerah yang selalu berkobar di hatinya? Dan lihatlah pula segala yang telah kau raih dari penderitaan dan kerja kerasmu selama ini. Kamu tentu tidak lupa mensyukuri itu, bukan? Karena telah banyak bukti bahwa kau berhasil melewati semuanya. Kini, tentu kau tak ingin persoalan remeh semacam ini mampu membuatmu kembali porak poranda. Ayolah, mulai kini, bangkitlah! Hapus kesedihan itu dari air matamu.”
Kuhapus lembayung airmata yang kembali mengalir di pipinya. Sendu. Ia semakin terisak. Aku selalu tak cukup memiliki kekuatan untuk menghadapi kesedihan perempuan yang aku kasihi. Walau bagaimanapun, pernah suatu kali aku larut dalam kesyahduan tatap matanya. Digenggamnya kemudian usapan tanganku. Ditujukannya tatap matanya yang berkaca-kaca itu padaku. Lekat-lekat. Ada sesuatu yang mengalir lambat-lambat. Menyelimuti suasana yang semakin muram dan dingin. Kesedihan itu tak mampu ditahannya lebih lama, dipacu oleh semacam kehendak untuk kembali bersandar pada harapan dan kasihnya selama ini. Maka dipeluknya tubuhku erat, melepaskan tangis dan sembilu yang bergulung di dadanya. Siapakah aku bila mengelak dari curahan cinta semacam ini. Kuusap pula tebar rambutnya. Mengalirkan kemesraan yang menghunjam. Dan di sela-sela ratapnya, ia berbisik lirih.
Maafkan aku. Aku akan tetap mencintaimu seperti matahari yang selalu menyinari bumi.
Dan sejak itu, waktu menelannya ke sebuah tempat tak bernama. Kami beranjak untuk saling melenyapkan diri. Memamah takdir hidup yang senantiasa tak terduga. Namun, di setiap musim, setiap aku memandang langit, di mana bintang-bintang bertahta dengan sempurna, ia serasa selalu hadir di suatu tempat, entah di mana. Mengukir kenangan, juga cinta yang mengendap. Dan di setiap menjelang fajar, kusaksikan ia bangkit dari peraduannya yang entah. Mengalirkan cinta yang bersinar hangat. Sebagaimana yang telah diucapkannya terakhir kali, sebelum ia melenyapkan diri.
Bandung, 170806
Maka bermanja-rialah sikapnya padaku. Kemesraan yang tak mampu terbendung. Kami habiskan waktu dengan masa bersama sepenuhnya. Serasa tak ada lagi waktu, karena dunia mungkin akan luluh lantak di esok hari. Dan hal yang paling indah baginya selalu, adalah memandang langit malam yang penuh tebaran bintang. Saat itu, kami akan luangkan waktu sejenak. Menghamparkan diri pada sebuah taman lapang untuk kemudian duduk atau berbaring menengadah. Mengagumi keindahan langit malam tanpa berdecak. Hanya sesekali kami berbincang, selebihnya adalah menyimpan tatap dan angan pada suatu ruang yang entah di mana.
Namun kali ini, aku merasa tak biasa. Resah yang selama ini menebar benih, telah menyubur, belukarnya terasa amat menyesakkan. Aku mengerti. Kami tak selamanya bisa bersama. Ini hanyalah sebuah kefanaan. Sesuatu yang akan pupus dihantam putaran waktu. Dan kami telah begitu saling mengerti. Menunggu satu sama lain untuk bersiap, berkemas, untuk kemudian menghilang. Mungkin inilah waktu itu. Dan sebagaimana perkiraanku, dialah yang akan melenyapkan diri terlebih dahulu.
Ia melamarku kemarin malam, ucapnya di sela waktu.
“Sungguh.”
Ya, awalnya sih aku kira bercanda, tapi sepertinya serius.
“Aku ngak tahu harus bilang apa. Kebanyakan perempuan akan bahagia bila dilamar. Selamat! Aku turut bahagia untukmu.”
Sungguh?
“Tentu saja.”
Ia menanggapinya dengan diam. Tiba-tiba aku menghirup nafas mendung di wajahnya.
“Kenapa? Ada masalah?”
Aku sedih.
“Ya, kelihatan di muka kamu.”
Aku harus bagaimana? tanyanya sunggguh-sunggguh.
“Secara harfiah, kalian seharusnya sudah sama-sama siap. Masalahnya, mungkin secara psikologis kamu masih bimbang. Tapi kamu sendiri telah tahu jawabannya. Banyak hal yang tak perlu dipertimbangkan, kamu hanya perlu melakukan.”
Sulit rasanya membayangkan harus memasrahkan segenap raga, juga sukma pada laki-laki yang tidak kucintai.
“Kamu berhak memilih. Tapi aku ragu kamu bisa. Pahamilah dari kini. Inilah kepatutan hidup. Setiap pilihan menyimpan setiap kemungkinan, juga kesulitan-kesulitan. Namun, ketika kau telah memutuskan, tak ada waktu lagi untuk membantah. Segalanya mesti kau terima dengan tabah. Yakinlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang penyabar. Dan kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang mulai belajar mencintai setelah mereka bersama. Aku yakin kamu bisa. Biarlah waktu yang nanti akan membantumu. Usailah meresahkan diri sendiri, suatu ketika akan kau temukan jawabannya.”
Hanya satu yang kini kupikirkan, katanya tiba-tiba.
“Apa?”
Kamu.
“Lho, kenapa dengan aku?”
Aku masih menginginkan kamu.
Kata-katanya menyimpan kesungguhan yang sempurna. Pandangannya menyergapku dengan lekat. Tapi kini aku telah begitu terbiasa dengan permohonan semacam ini. Telah lama, terlalu lama. Kami selalu memperdebatkan hal yang sama. Namun, tak juga kunjung kami mengerti segala yang terjadi.
“Kita sudah bicara banyak tentang ini. Hadapilah kenyataan. Sudah tak ada takdir untuk kita. Aku hanya persinggahan sejenak.”
Kenapa aku tak bisa memiliki orang yang aku cintai? tanyanya kembali dengan lantang.
“Kenyataannya bahwa sebagian besar perempuan tampaknya tidak terlalu membutuhkan laki-laki yang dia cintai, sebaliknya ia lebih perlu laki-laki yang mencintanya. Suatu saat kamu akan sadari itu.”
Sepertinya ia tak terlalu puas dengan sebuah jawaban. Kembali ditatapnya mataku lekat dan erat. Dahinya berkerut. Sebuah tanda bahwa ia berpikir banyak-banyak. Dan pertanyaan yang ia lontarkan kemudian begitu pekat dengan rasa curiga.
Katakan! Apakah kau juga menginginkanku sebagaimana aku menginginkanmu?
“Sejujurnya,” ucapku dengan mencoba mengais setiap kemungkinan untuk sebuah jawaban yang terbaik, “aku pernah menginginkanmu.”
Pernah?
“Ya, pernah. Tapi kita sama-sama tahu. Impian itu kandas sejak .... Ah, mungkin kita tak perlu mengungkit masa lalu. Untuk kemudian hanya akan mengungkap kenangan buruk. Lalu berdebat tentang penyesalan, cinta, juga airmata. Dan kita, kemudian akan kembali berputar-putar di tempat yang sama.”
Apakah kini kau tidak lagi mencintaiku?
“Tentu tidak mudah melupakan cinta. Aku masih mengasihimu. Itu benar. Tapi kita telah sama-sama mengerti kesulitan yang kita hadapi. Pengalaman hidup mengajarkan aku untuk berlaku bijak dan tabah. Setelah banyak aku kehilangan sesuatu. Bahkan untuk yang paling pedih sekalipun. Kini, kita mesti banyak belajar untuk mencintai tanpa takut kehilangan.”
Tapi aku tak ingin kehilangan kamu. Aku ingin terus mencintaimu. Aku ingin tetap memilikimu. Selalu sampai kapanpun.
Perasaannya kian meluap serupa ombak pasang.
“Tentu, aku tak bisa memaksamu untuk berhenti mencintaiku. Hanya hatimu sendiri yang mampu melakukannya. Tapi ada orang lain yang mungkin lebih berhak memilikimu. Seseorang yang dulu telah kau pilih. Tak perduli walau rasa penyesalan itu masih selalu menjeratmu. Aku yakin, waktu bisa mengatasi segalanya, tak terkecuali cinta. Lambat laun aku akan tergantikan, cinta ialah ibarat jamur di musim penghujan. Akan muncul dengan tiba-tiba. Karena itu, bukakanlah hatimu. Belajarlah untuk mencintainya dan kau akan menemukan kasih sejatimu.”
Malam bertambah malam. Aliran dingin menyergap suasana. Menyelusup ke dasar hati yang terdalam. Dan sedikit demi sedikit membangkitkan kekecewaannya akan harapan yang tak berbalas.
Sepertinya kamu senang ya, kalau aku pergi dari kamu? Agar kamu juga bisa pergi ke lain hati, kan?
“Tak baik berburuk sangka. Tentu orang-orang akan yang bersedih jika kehilangan orang terdekatnya, tak terkecuali aku. Demi Tuhan, aku akan sedih kehilanganmu. Kita tak mampu bersama bukan karena sebuah alasan, tetapi lebih karena sebuah keniscayaan. Tak pernah ada sesuatu yang abadi, pun untuk hidup itu sendiri. Segalanya hanya sebuah kesementaraan. Sadarilah arti perpisahan sebelum memulai sebuah pertemuan. Pahamilah makna luka ketika akan tertawa. Karena perpisahan kadang juga menyimpan setumpuk pelajaran dan kebaikan. Suatu saat kau akan mengerti itu, aku yakin.”
Aku tuh nekad banget ya, terlalu memaksakan kehendak, ujarnya kemudian.
“Aku telah mengenalmu jauh dari yang kamu kira. Kamu pemberani, seperti pejuang. Tegar bagai karang, berkobar laksana api. Telah banyak yang kamu hadapi. Dan itu membuatmu belajar untuk terus bertahan tanpa menyerah. Karena menyerah adalah berarti pupus. Tergilas kenyataan yang tak memihak. Hidup mengajarkan kamu untuk memaksakan setiap cara, juga kemungkinan. Aku tak pernah menyalahkan kamu demi alasan semacam itu. Sunggguh, aku sangat bermaklum diri.”
Tak bisakah kamu seperti aku. Mempertahankan apa yang kita rasakan?
“Aku mempertahankan apa yang sebaiknya aku pertahankan. Dan itu telah berlalu sejak kepergianmu waktu itu. Lagi pula, aku tak pernah mengemis apa pun pada siapa pun. Sebab beginilah aku adanya, menerima apa yang berhak aku terima. Dan melepaskan apa yang tak berhak aku pertahankan.”
Kamu pengecut. Kamu tak punya keberanian untuk menentang kenyataan, tuduhnya dengan keras.
Aku menghela nafas. Sekadar menghembuskan keriuhan yang menumpuk di dadaku. Sungguh, betapa aku mencoba memaparkan setiap penjelasan dengan bijak dan seksama. Namun, ketika logika dikalahkan prasangka, maka tak pernah ada penafsiran yang sama. Aku dan dirinya selalu bersimpang pemikiran.
“Sebaliknya,” lanjutku kembali, “aku belajar meneguhkan hati dan mengalahkan setiap ketakutan untuk tetap bersikukuh pada apa yang telah aku yakini. Ketahuilah, aku telah banyak mencoba dan itu sudah cukup bagiku. Aku harus memamah setiap kekhawatiran dan mengingkari kenyataan bahwa aku masih mengasihimu. Dan jalan hidup mengharuskan kita untuk tak lagi memaksakan perasaan. Lagi pula, siapa yang mampu menolak kenyataan, pun tidak untukmu. Kita telah sama-sama tahu itu.”
Tapi ini bukan hal yang kuinginkan. Aku terperangkap. Dan hidup —entah bagaimana caranya— telah memaksaku untuk tak bisa mengelak dari keharusan yang menyebalkan ini.
“Aku paham. Itulah sebabnya aku mencoba untuk selalu terbuka memaafkan setiap kesalahan di masa lalumu. Dan menerimamu untuk bersama walau sesaat, sebelum kau benar-benar pergi. Karena itu, seharusnya kita tak perlu memperdebatkan semuanya. Kita telah cukup lelah dengan itu semua. Kini, sandarkan bebanmu padaku. Aku tahu, kamu begitu penat setelah banyak bergulat dengan keharusan hidup. Menepilah di sini, dalam pelukanku. Ada secangkir kasih yang hangat untukmu.”
Sejenak gundahnya mereda. Aku tak bisa meneruskan persengketaan ini. Semacam lorong-lorong gelap tak bertepi. Di mana hanya kebuntuan yang akan kutemui setelahnya. Mungkin rayuan semacam itu bisa menghilangkan resahnya walau sesaat. Ia pun tersadar sejenak. Kemudian mengibaskan butiran mutiara yang telah mulai berderai dari tatapnya. Perlahan ia sandarkan tubuhnya dalam dekapku. Dan kembali menatap kerlip bintang di lautan malam.
Ah, aku menyesali masa lalu. Kini aku merasa begitu bodoh hingga pernah meninggalkan orang yang begitu kucintai.
“Tak perlu menyesal. Karena kini kita masih bisa bersama. Lupakan apa yang telah dan seharusnya terjadi. Segalanya telah berlalu dan menjadi pelajaran bagi kita. Kini, nikmatilah waktu yang tersisa. Kita curahkan dengan kenangan indah dan ingatan-ingatan yang tak akan terlupakan.”
Aku khawatir kau akan pergi dariku? katanya kembali.
“Tidak, aku akan tetap ada di sini. Mungkin untuk terus mengenangmu. Karena hidup juga menyisakan banyak ingatan yang tak terlupakan. Tapi kita terlarang untuk terus tenggelam di dalamnya. Karena bayang-bayang masa lalu ialah semacam lorong-lorong labirin tak berujung. Sungguh teramat menyesatkan. Sebaliknya, mungkin aku juga perlu untuk memulai hidup baru. Lepas dari jerat rutinitas satu, untuk kemudian terperangkap ke lain rutinitas. Bukankah hidup harus terus dijalani. Dan kita masih punya impian, bukan? Ada banyak cara untuk mewujudkannya. Walau hidup selalu memberikan berbagai macam kemungkinan yang tak terduga. Dan kita akan selalu kalah bila bertaruh tentang apa yang akan terjadi. Tapi setiap kemungkinan menyimpan harapan, pengalaman, dan pelajaran baru tentang hidup itu sendiri.”
Lalu, setelah ini kau akan bersama siapa?
“Jangan khawatir, masih ada banyak orang yang berharap dan menungggu. Aku tidak akan kesepian tanpamu. Tapi tidak dalam waktu dekat, karena untuk saat ini aku harus banyak menenangkan diri. Berbenah dengan perasaan dan pikiran yang telah lama tak beraturan. Tetap doakan aku untuk bahagia, sebagaimana juga aku selalu mendoakanmu.”
Tapi aku tetap tak ingin kita berpisah. Tuh kan, akhirnya aku selalu merasa kalah. Dan kamu selalu membuat aku merasa semakin kalah. Kenapa sih, apa yang aku ingini ngak pernah bisa terjadi, untuk sekali ini saja.
Lembaran kaca kembali berlinang dalam tatapnya.
“Pandailah bersyukur. Mengapa kita selalu lupa dengan semua yang telah diberikan hidup untuk kita, tapi tak pernah lupa segala yang tidak diberikan hidup untuk kita. Aku tahu, telah banyak pedih yang kamu jalani hingga kamu seperti sekarang ini. Ada banyak cobaan, aral, dan rintang. Tentu itu menyakitkan. Puncak tinggi tak berjalan landai, tapi keras dan terjal. Keindahan menanti dipuncaknya. Dan lihatlah sekarang. Telah lahir sesosok yang baru, seseorang perempuan yang setegar karang. Tak perduli walau onak dan duri tertancap di hatinya. Bahkan mampu menahan badai dan hujan sekalipun. Seorang perempuan yang juga memiliki kepercayaan diri setinggi langit dengan semangat berjuang dan pantang menyerah yang selalu berkobar di hatinya? Dan lihatlah pula segala yang telah kau raih dari penderitaan dan kerja kerasmu selama ini. Kamu tentu tidak lupa mensyukuri itu, bukan? Karena telah banyak bukti bahwa kau berhasil melewati semuanya. Kini, tentu kau tak ingin persoalan remeh semacam ini mampu membuatmu kembali porak poranda. Ayolah, mulai kini, bangkitlah! Hapus kesedihan itu dari air matamu.”
Kuhapus lembayung airmata yang kembali mengalir di pipinya. Sendu. Ia semakin terisak. Aku selalu tak cukup memiliki kekuatan untuk menghadapi kesedihan perempuan yang aku kasihi. Walau bagaimanapun, pernah suatu kali aku larut dalam kesyahduan tatap matanya. Digenggamnya kemudian usapan tanganku. Ditujukannya tatap matanya yang berkaca-kaca itu padaku. Lekat-lekat. Ada sesuatu yang mengalir lambat-lambat. Menyelimuti suasana yang semakin muram dan dingin. Kesedihan itu tak mampu ditahannya lebih lama, dipacu oleh semacam kehendak untuk kembali bersandar pada harapan dan kasihnya selama ini. Maka dipeluknya tubuhku erat, melepaskan tangis dan sembilu yang bergulung di dadanya. Siapakah aku bila mengelak dari curahan cinta semacam ini. Kuusap pula tebar rambutnya. Mengalirkan kemesraan yang menghunjam. Dan di sela-sela ratapnya, ia berbisik lirih.
Maafkan aku. Aku akan tetap mencintaimu seperti matahari yang selalu menyinari bumi.
Dan sejak itu, waktu menelannya ke sebuah tempat tak bernama. Kami beranjak untuk saling melenyapkan diri. Memamah takdir hidup yang senantiasa tak terduga. Namun, di setiap musim, setiap aku memandang langit, di mana bintang-bintang bertahta dengan sempurna, ia serasa selalu hadir di suatu tempat, entah di mana. Mengukir kenangan, juga cinta yang mengendap. Dan di setiap menjelang fajar, kusaksikan ia bangkit dari peraduannya yang entah. Mengalirkan cinta yang bersinar hangat. Sebagaimana yang telah diucapkannya terakhir kali, sebelum ia melenyapkan diri.
Bandung, 170806
14 August 2006
Me in Half

tubuhku membelah dua, menjadi tiga, lima
bahkan terpotong seribu
sukmaku menjelma serpihan kalut, airmata,
juga sunyi yang menganak sungai
O, sampai di mana tatapku, Ibu
sedang langit tak jua tergapai
sedang dasar tak kunjung dangkal
sedang ranting tak lagi puncak
sedang matamu
belum juga masak
penuh kemelut dendam
bandung, 140806
09 August 2006
AKu dan Kau pada Suatu Waktu
Mengapa kau selalu saja menimbun-nimbun masa lalu. Sedang kita belum juga memastikan akan ke mana kita melangkah. Kenangan pahit ialah semacam labirin tak berujung, yang hanya akan membuat kita tersesat di dalamnya, masih juga kau tangisi kepergiannya, sementara jejak yang ia tinggalkan telah begitu lama tersapu angin dan hujan. Lalu untuk apa pula aku ada di sini jika tidak untuk berbagi. Sia-sia saja kau tangisi, sampai kapan pun juga ia tak akan kembali.
Mungkin kau masih ingat, kutemukan kau di sela-sela tangismu sore itu, di sebuah taman yang muram. Kekasihmu pergi dan kau masih tak rela untuk melepasnya. Apalagi yang harus kukatakan saat itu, selain beberapa patah kata untuk ketegaranmu. Akhirnya, lambat laun tangismu itu mereda, dan kau mulai mencoba untuk tersenyum ketika di kejauhan sana kau melihat tiga orang bocah berlari-lari kecil dan bermain-main untuk kemudian terjatuh. Teringat masa kecil, ujarmu.
Tapi itu bukan kali pertama dan terakhir. Di waktu yang lain, aku pernah menjumpaimu tengah meratapi foto usang laki-laki yang telah meninggalkanmu itu. Hatiku bergejolak dan sesak. Terlebih kau hanya mampu untuk menangis. Apalagi yang harus kulakukan, aku hanya tak ingin melihatmu bersedih karenanya. Maka kurampas foto itu darimu, lalu kurobek menjadi bagian-bagian kecil yang tak mudah lagi untuk dikenali. Kau pun marah dan menamparku. Mencaci maki dengan kata–kata kotor dan kejam. Aku hanya terdiam. Dan airmata pun kian menderas tumpah di pipimu yang senantiasa memerah. Namun, tiba-tiba kau seperti tersadar telah melakukan suatu kesalahan. Di sela-sela tangismu kau meminta maaf, kau katakan bahwa kau sangat merindukannya untuk kembali, walau sebenarnya itu adalah hal yang tak mungkin terjadi. Dan itu membuat aku kian tak mengerti.
Keesokan harinya kau hadir dalam keceriaan, tapi aku belum juga mampu untuk menerka arti kegembiraanmu itu. Kutatap lekat-lekat bola matamu yang berbinar-binar. Lalu kukatakan saja bahwa kau tampak begitu memesona dengan tatap mata yang seperti itu. Kau tersenyum, lalu bertanya tentang sesuatu yang paling aku harapkan selama ini. Aku tak perlu waktu lama untuk berpikir, karena hal yang paling kuharapkan adalah saat-saat untuk selalu bersamamu, kapan pun dan di mana pun. Tapi tentunya aku tak seterus terang itu. Kukatakan saja padamu bahwa aku sangat mengharapkan kebahagiaan. Sebuah jawaban yang sangat klise dan abstrak. Kau pun tersenyum dan mendoakan semoga aku mendapatnya. Akan tetapi, ketika aku kembali bertanya tentang hal yang paling kau harapkan, segalanya berubah dengan tiba-tiba. Pandanganmu menunduk. Wajahmu mengabarkan kemuraman yang meraja. Kau mengalihkan pembicaraan dan berpaling seketika. Ah, sepertinya aku telah salah bicara. Entahlah.
Lalu kau pun menjalani keseharian dengan sebagaimana mestinya. Rutinitas yang biasa kau jalani. Kau adalah seorang putri pembesar. Segalanya bisa kau miliki tanpa terkecuali. Sementara aku hanyalah seorang penjual bunga yang berada tak jauh dari rumahmu. Hanya sesekali kita berjumpa. Itu pun jika kerinduanmu akan bunga-bunga telah menjerat rutinitas kerjamu. Aku adalah pungguk. Sedangkan kau adalah rembulan yang begitu dirindukan. Tapi kau bukanlah seorang yang angkuh, karena pada akhirnya perlahan-lahan telah kita bina hubungan baik yang sekadarnya.
Kita adalah sahabat baik yang sama-sama menyukai bunga, begitu katamu selalu. Tapi aku mengelak karena entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saja aku menaruh hati padamu, tentu saja saat itu aku hanya bisa mengungkapkannya dalam anganku sendiri, karena aku tahu bahwa mengungkapnya padamu hanya akan membuat semua yang telah kita bina selama ini menjadi porak poranda. Biarlah, hal itu kusimpan baik-baik, hingga tiba saat yang sungguh-sungguh tepat.
Selebihnya, aku mencoba untuk membangun dan menciptakan hal-hal yang indah bersamamu. Hingga suatu saat, kalau pun impianku kandas, setidaknya ada hal-hal membahagiakan yang pernah kita kenang. Semacam perjalanan-perjalanan manis yang pernah kita lalui dengan menyenangkan. Membawamu dalam rasa ceria dan tawa yang renyah, juga senyum yang menawan. Pernahkah kau ingat, di suatu senja yang merona, kubawa kau menuju ladang bunga. Kita hirup tebaran aroma bunga-bunga yang tengah memekarkan diri. Lalu, kita petik bunga-bunga itu bersama. Setelah sebelumnya kuajari kau cara menanam, merawat, memetik, dan menyiram bunga dengan cara yang tak biasa. Di tengah kebersamaan kita, kau berkata ingin menjelma bunga. Ia adalah perlambang cinta dan warna hidup, katamu saat itu. Ia hadir dengan kecantikan dan pesona yang sempurna. Dikagumi dan dipuja siapa pun. Dinantikan dan diharapkan kapan pun. Ah, sebuah impian yang indah. Jika demikian, menjelmalah bunga di taman hatiku. Akan kurawat, kusirami, dan kujaga senantiasa hingga ia tumbuh dan memekarkan diri dengan pesona dan keharuman yang abadi. Tapi kenyataan ternyata tak semudah harapan. Mengharapkannya berarti sejauh jarak yang terbentang antara langit dan bumi. Hanya mimpi yang tak kan tergapai.
Namun, aku tahu, sangat tahu, di sela-sela keriangan wajahmu, ada sesuatu yang mengendap, kesedihan yang kau tebar menjadi lumut-lumut penghuni kedalaman. Sesuatu yang tak terkatakan, tapi begitu kau rasakan. Belenggu yang menjeratmu hingga kemana pun kau melangkah. Ketahuilah bahwa aku telah terbiasa untuk menangkap banyak hal yang kau simpan. Mungkin ada banyak alasan yang bisa kau ciptakan. Ada banyak kebenaran yang ingin kau tutupi. Tapi mungkinkan segalanya bisa terhindari? Sementara segenap rasa kehilangan itu masih juga kau bawa serta.
Ada banyak alasan untuk mempertahankan cinta. Sebagaimana juga ada banyak alasan alasan untuk melepaskannya. Dan kau adalah jenis perempuan yang begitu memuja kesetiaan. Tak mampu perpaling ke lain hati walau telah kau jumpai pula cinta sepahit empedu. Rasa kehilangan itu tak juga mampu kau pupuskan. Sebaliknya, sedikit demi sedikit, kau simpan menjadi tumpukan karang yang tak kan goyah dihantam seribu gelombang sekalipun. Ada banyak cara untuk memupuskan sedih, tapi kau telah memilih jalan yang paling sesat.
To be Continued
Mungkin kau masih ingat, kutemukan kau di sela-sela tangismu sore itu, di sebuah taman yang muram. Kekasihmu pergi dan kau masih tak rela untuk melepasnya. Apalagi yang harus kukatakan saat itu, selain beberapa patah kata untuk ketegaranmu. Akhirnya, lambat laun tangismu itu mereda, dan kau mulai mencoba untuk tersenyum ketika di kejauhan sana kau melihat tiga orang bocah berlari-lari kecil dan bermain-main untuk kemudian terjatuh. Teringat masa kecil, ujarmu.
Tapi itu bukan kali pertama dan terakhir. Di waktu yang lain, aku pernah menjumpaimu tengah meratapi foto usang laki-laki yang telah meninggalkanmu itu. Hatiku bergejolak dan sesak. Terlebih kau hanya mampu untuk menangis. Apalagi yang harus kulakukan, aku hanya tak ingin melihatmu bersedih karenanya. Maka kurampas foto itu darimu, lalu kurobek menjadi bagian-bagian kecil yang tak mudah lagi untuk dikenali. Kau pun marah dan menamparku. Mencaci maki dengan kata–kata kotor dan kejam. Aku hanya terdiam. Dan airmata pun kian menderas tumpah di pipimu yang senantiasa memerah. Namun, tiba-tiba kau seperti tersadar telah melakukan suatu kesalahan. Di sela-sela tangismu kau meminta maaf, kau katakan bahwa kau sangat merindukannya untuk kembali, walau sebenarnya itu adalah hal yang tak mungkin terjadi. Dan itu membuat aku kian tak mengerti.
Keesokan harinya kau hadir dalam keceriaan, tapi aku belum juga mampu untuk menerka arti kegembiraanmu itu. Kutatap lekat-lekat bola matamu yang berbinar-binar. Lalu kukatakan saja bahwa kau tampak begitu memesona dengan tatap mata yang seperti itu. Kau tersenyum, lalu bertanya tentang sesuatu yang paling aku harapkan selama ini. Aku tak perlu waktu lama untuk berpikir, karena hal yang paling kuharapkan adalah saat-saat untuk selalu bersamamu, kapan pun dan di mana pun. Tapi tentunya aku tak seterus terang itu. Kukatakan saja padamu bahwa aku sangat mengharapkan kebahagiaan. Sebuah jawaban yang sangat klise dan abstrak. Kau pun tersenyum dan mendoakan semoga aku mendapatnya. Akan tetapi, ketika aku kembali bertanya tentang hal yang paling kau harapkan, segalanya berubah dengan tiba-tiba. Pandanganmu menunduk. Wajahmu mengabarkan kemuraman yang meraja. Kau mengalihkan pembicaraan dan berpaling seketika. Ah, sepertinya aku telah salah bicara. Entahlah.
Lalu kau pun menjalani keseharian dengan sebagaimana mestinya. Rutinitas yang biasa kau jalani. Kau adalah seorang putri pembesar. Segalanya bisa kau miliki tanpa terkecuali. Sementara aku hanyalah seorang penjual bunga yang berada tak jauh dari rumahmu. Hanya sesekali kita berjumpa. Itu pun jika kerinduanmu akan bunga-bunga telah menjerat rutinitas kerjamu. Aku adalah pungguk. Sedangkan kau adalah rembulan yang begitu dirindukan. Tapi kau bukanlah seorang yang angkuh, karena pada akhirnya perlahan-lahan telah kita bina hubungan baik yang sekadarnya.
Kita adalah sahabat baik yang sama-sama menyukai bunga, begitu katamu selalu. Tapi aku mengelak karena entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saja aku menaruh hati padamu, tentu saja saat itu aku hanya bisa mengungkapkannya dalam anganku sendiri, karena aku tahu bahwa mengungkapnya padamu hanya akan membuat semua yang telah kita bina selama ini menjadi porak poranda. Biarlah, hal itu kusimpan baik-baik, hingga tiba saat yang sungguh-sungguh tepat.
Selebihnya, aku mencoba untuk membangun dan menciptakan hal-hal yang indah bersamamu. Hingga suatu saat, kalau pun impianku kandas, setidaknya ada hal-hal membahagiakan yang pernah kita kenang. Semacam perjalanan-perjalanan manis yang pernah kita lalui dengan menyenangkan. Membawamu dalam rasa ceria dan tawa yang renyah, juga senyum yang menawan. Pernahkah kau ingat, di suatu senja yang merona, kubawa kau menuju ladang bunga. Kita hirup tebaran aroma bunga-bunga yang tengah memekarkan diri. Lalu, kita petik bunga-bunga itu bersama. Setelah sebelumnya kuajari kau cara menanam, merawat, memetik, dan menyiram bunga dengan cara yang tak biasa. Di tengah kebersamaan kita, kau berkata ingin menjelma bunga. Ia adalah perlambang cinta dan warna hidup, katamu saat itu. Ia hadir dengan kecantikan dan pesona yang sempurna. Dikagumi dan dipuja siapa pun. Dinantikan dan diharapkan kapan pun. Ah, sebuah impian yang indah. Jika demikian, menjelmalah bunga di taman hatiku. Akan kurawat, kusirami, dan kujaga senantiasa hingga ia tumbuh dan memekarkan diri dengan pesona dan keharuman yang abadi. Tapi kenyataan ternyata tak semudah harapan. Mengharapkannya berarti sejauh jarak yang terbentang antara langit dan bumi. Hanya mimpi yang tak kan tergapai.
Namun, aku tahu, sangat tahu, di sela-sela keriangan wajahmu, ada sesuatu yang mengendap, kesedihan yang kau tebar menjadi lumut-lumut penghuni kedalaman. Sesuatu yang tak terkatakan, tapi begitu kau rasakan. Belenggu yang menjeratmu hingga kemana pun kau melangkah. Ketahuilah bahwa aku telah terbiasa untuk menangkap banyak hal yang kau simpan. Mungkin ada banyak alasan yang bisa kau ciptakan. Ada banyak kebenaran yang ingin kau tutupi. Tapi mungkinkan segalanya bisa terhindari? Sementara segenap rasa kehilangan itu masih juga kau bawa serta.
Ada banyak alasan untuk mempertahankan cinta. Sebagaimana juga ada banyak alasan alasan untuk melepaskannya. Dan kau adalah jenis perempuan yang begitu memuja kesetiaan. Tak mampu perpaling ke lain hati walau telah kau jumpai pula cinta sepahit empedu. Rasa kehilangan itu tak juga mampu kau pupuskan. Sebaliknya, sedikit demi sedikit, kau simpan menjadi tumpukan karang yang tak kan goyah dihantam seribu gelombang sekalipun. Ada banyak cara untuk memupuskan sedih, tapi kau telah memilih jalan yang paling sesat.
To be Continued
Lima Huruf Menuju Sunyi
Kala itu, diam adalah malam. Ia kembali mencerna resah. Terperangkap sebuah tempat di mana waktu sepertinya tak mau lagi menunggu. Telah lama ia terpendam di sana. Dalam kesenyapan. Sementara layar komputer tetap menyala. Menunggu sesuatu, entah, mungkin tentang sebuah kata atau apapun yang akan ia goreskan di sana. Segalanya selalu menanti, menanti, dan menanti, tanpa kepastian.
“Ia pergi dan tak akan pernah kembali,” lirihnya.
Seperti ada semacam keberanian yang menyelinap di antara aliran darahnya. Jari-jari kurusnya yang selalu bergetar itu kini mulai bergerak. Tombol huruf C di atas papan keyboard ditujunya. Sepermilimeter lagi jari-jari itu akan sampai, namun tiba-tiba terhenti dan kemudian ditariknya kembali. Keengganan bergemuruh di dadanya yang hampa. Ia kembali terjelembab. Matanya bergetar. Kesedihan itu rupanya telah merasuk dalam. Tetes-tetes airmata pun kini menggembang. Sebuah kata tentang luka mengingatkannya akan kisah masa lalu yang pedih. Tubuhnya kini meringkuk. Kedua lutut ia rekatkan, kepalanya ia benamkan dalam isak tangis yang sendu. Walaupun jauh di lubuk hatinya, ia telah merasa malu untuk terus-menerus bersedih.
Tiba-tiba tangisnya terhenti. Ada amarah yang berkilat di matanya. Wajah angkuhnya ia tegakkan. Tubuhnya pun bagai diguncang gempa yang hebat. Di antara denting-denting waktu, ia berteriak keras, menggetarkan dinding-dinding kamar yang telah lama kosong dan lembab. Dan turut pula memecah malam di luar sana, yang kini lelap dengan dinginnya angin malam yang berhembus tajam.
“Persetan dengan airmata!” serunya pada diri sendiri.
Namun akankah ia mengerti bahwa ada sesuatu yang hingga kini tak bisa ia ingkari, dan sampai kapanpun tak akan pernah bisa ia ingkari. Sesuatu yang mengganjal di lelap mimpinya. Semacam ombak yang senantiasa bergulung menghantam pantai. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar airmata dan kesedihan: kenyataankah? Entah.
Kesendirian ini tentunya hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah kini tak ada lagi yang rela untuk menampung segenap asa dan kerinduannya itu. Kesendirian yang begitu rapi ia simpan di setiap hembusan nafasnya yang nestapa. Dan kesendirian, baginya kini ialah pintu kamar yang terkunci rapat, jendela yang terpaku, lubang ventilasi yang terisolasi, dan tentunya suara yang terbungkam, juga segala sesuatu yang hanya bisa ia nikmati sendiri.
Tajam tatapnya kembali menuju layar komputer. Harus ada yang terselesaikan, pikirnya. Tanpa terasa bulatan putih matanya kian memerah. Seperti bara api yang senantiasa menyimpan amarah. Lalu hamparan puisi yang sedari tadi berceceran di sekitarnya, diraihnya kembali. Dengan beringas ia tampak mencari-cari. Pikirannya menyeruak suasana.
“Kata…kata…kata…kata…,” ucapnya pada hamparan puisi itu.
Ia menemukan sesuatu, ya, sesuatu. Selembar puisi diraihnya erat-erat. Lalu dibacanya pula dalam diam. Bibir keringnya tampak gemetar. Ia pun memejamkan mata. Pikirannya seperti tengah meresapi mantra-mantra yang hakiki. Absurditas yang biasa ia puja di setiap aliran waktu. Keliaran imajinasi yang pasti akan membawanya ke dalam ruang di mana realita dan sesuatu yang semu seakan tiada bedanya. Tubuh kasarnya terdiam tanpa gerak. Bahkan mungkin tanpa nafas, tanpa denyut nadi, dan tanpa detak jantung sekalipun. Namun wajahnya menampakan ketenangan, didekap kehampaan yang paling sublim. Sekali lagi, sebuah kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Keheningan yang kian menggelora, tapi ia sama sekali tak merasa kehilangan apapun. Hanya sebuah keterasingan yang lepas dari sebuah rutinitas hidup, teramat merdeka, tak terjajah oleh sesuatu.
Perlahan-lahan kini pelupuk matanya membuka. Jiwanya seakan baru saja terlahir kembali dari sebuah rahim bernama sunyi, yang telah mengandungnya selama berabad-abad. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sungguh, kegelisahannya kini mereda sesaat. Seperti kemarau di tengah gurun sahara yang gersang, tiba-tiba terguyur hujan lebat yang menyejukan.
“Sebait puisi,…ah, tidak! Aku telah terlalu lelah dengan puisi. Namun apalagi kini yang harus aku renungi. Oh, Tuhan, jangan biarkan aku senantiasa terpuruk di dalamnya…” kata-katanya terhenti seketika.
Dipandanginya layar komputer kembali. Ia tersentak. Ada huruf C terpampang di lembaran putih komputernya. Aneh, ia merasa belum sempat untuk menekan tombol huruf C. Namun, kini tidak ada waktu untuk bertanya-tanya lagi. Jawaban telah menjelma labirin-labirin hampa di otaknya. Tanpa sadar, jari telunjuknya kini telah menekan tombol huruf C dengan kelelapan yang panjang. Terpampanglah seketika deretan huruf C yang berjejer rapi. Setelah sampai pada baris kedua, ia baru tersadar.
“Oh, apa yang telah kulakukan?” sesalnya pada diri sendiri.
Sebenarnya sesal ialah sesuatu yang teramat ia benci. Baginya, sesal hanyalah perbuatan bodoh manusia. Pertanda ketidakyakinan atas apa yang telah dilakukan, ketidaksadaran atas setiap resiko yang hadir di setiap langkah kehidupan, dan semacam ketidakmampuan menerima segala ketentuan yang telah digariskan oleh Sang Penentu. Sementara waktu, toh, tak pernah bisa berbalik arah, lalu untuk apa manusia harus merasa menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Namun, pendiriannya kini adalah semacam konsekuensi dari luka yang pernah dideritanya di masa lalu. Ia tiba-tiba teringat pada suatu masa di mana ia pernah mengalami sebuah penyesalan yang begitu mendalam. Sebuah kisah yang melankolis, tetapi berakhir dengan goresan derita hingga seumur hidupnya. Tentang seorang perempuan berwajah hujan, tentang cinta yang pernah bersemi, tentang dahaga dan hampa yang terpuaskan, tentang kemesraan yang mendesah, dan tentang sebuah pelukan yang senantiasa hangat. Sekian lama ia terbuai di dalamnya, larut di antara kesyahduan yang membunga. Sehingga suatu kali, pernah juga ia banyak mengucap puji syukur kepada Tuhan karena telah sudi menciptakan makhluk bernama perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Bukankah satu sama lainnya tak pernah bisa hidup sendiri. Namun, realita sepertinya tak pernah memihak pada manusia semacam dirinya. Harapan yang tak sejalan dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, perempuan yang telah sekian lama dipujanya itu, tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali. Entah kemana dan mengapa.
“Kesetiaan rupanya tak pernah bisa benar-benar bermakna,” ucapnya waktu itu, di antara waktu yang berguguran.
Ketabahannya roboh seketika. Penyesalan perlahan-lahan menyusupi denyut nadinya, desah nafasnya, detak jantungnya, bahkan setiap helai jiwanya. Ia menyesal telah terbuai bujuk perasaan yang seharusnya tak patut ia percayai. Dan ia pun menyesal karena telah mengabaikan bisik logika yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Itulah di mana ia pernah merasakan penyesalan untuk yang pertama kalinya dan sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya, ia pun menyesal karena telah merasa menyesal. Sejak itulah, ia mengasingkan diri, mencoba memahami kembali segalanya dengan meresapi segenap kesendirian dan sunyi.
Layar komputer masih menunggunya untuk berkata. Ada bisik hati yang menuntun jari telunjuk kanannya untuk menekan tombol huruf I. Sejenak pikirannya bimbang akan sesuatu. Dan kini, ia teramat merasa ragu-ragu. Seribu pertanyaan pun berkecamuk: mengapa harus huruf I, mengapa tidak huruf yang lain saja, ada apa dengan huruf I, begitu berartikah huruf I, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun ia terlambat, sebuah kekuatan asing menarik jari telunjuk kanannya untuk menekan tombol huruf I. Akhirnya terpampanglah di layar komputer, huruf I yang tegak dengan angkuhnya.
“Mengapa aku tak pernah mampu untuk mengeja hidupku sendiri,” teriaknya dalam kekesalan.
Lembaran puisi yang berserakan, layar komputer yang mengambang, ruang yang kosong, dan kesendirian yang hampa, menggambarkan kepedihannya yang semakin meraja. Pernah pula ia berspekulasi, mencoba untuk mengerti arti hidup melalui 1001 jalan kematian.
“Bukankah setiap yang hidup itu pasti mati. Lalu untuk apalagi aku menundanya, jika hidup pun aku serasa mati,” ujarnya saat itu.
Karena itu, beberapa kali ia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri, baik itu dengan terjun bebas dari ketinggian puluhan meter tanpa pengaman dengan kepala berada di bawah, membakar tubuhnya sendiri dengan guyuran bensin, meminum racun yang paling mematikan, menggantung lehernya di tiang gantungan, menenggelamkan diri di lautan, menusuk jantungnya dengan senjata tajam, maupun menembak kepalanya dengan pistol sungguhan. Namun Tuhan sepertinya belum berkehendak ia mati. Dan setiap kali percobaan bunuh diri itu dilakukannya, setiap kali pula ada keajaiban yang membuatnya masih tetap hidup. Dalam kegagalannya, akhirnya ia pun tersadar bahwa terlalu bodoh bagi dirinya untuk sekadar berputus asa, naif, dan sia-sia.
Ia kemudian kembali teringat pada lembaran puisi yang berserakan itu. Dipandanginya satu persatu dengan cermat. Mungkin ada jutaan huruf, ribuan kata, dan ratusan kalimat di sana. Adakah yang paling istimewa di antaranya, pikirnya. Tanpa sadar, ada sebuah huruf yang paling menggoda tatapnya di antara jutaan huruf, ribuan kata, dan ratusan kalimat itu. Ia menemukan huruf N, ya, huruf N. Baginya, huruf itu begitu memesona, entah mengapa. Tanpa ragu lagi, sebuah jari tangannya digerakkan menekan tombol huruf N, maka tercetaklah di layar komputer itu huruf N, setelah huruf C dan I.
Walaupun begitu, ia masih merasa kehilangan sesuatu. Seketika terbersit keinginannya untuk mengadu, tapi pada siapa, pada apa, dan mesti bagaimana. Sesungguhnya ada dua tempat yang pernah menjadi tempatnya mengadu. Pertama, yaitu perempuan yang kini telah pergi dan tidak akan pernah kembali itu. Sementara yang kedua adalah orang tua kandungnya yang juga kini telah tiada. Tentang kedua orang tuanya, ia banyak mengenang, yaitu masa ketika kedua orang tuanya masih selalu berada di sampingnya, melindunginya, menyayanginya, dan senantiasa membuatnya berarti. Ayahnya ialah seorang pejuang. Ia gugur ketika melawan penjajah, namun jasadnya tidak berada di taman makam pahlawan karena pemerintah tidak pernah berani mengakuinya sebagai pahlawan. Tapi walau bagaimanapun, ia yakin bahwa ayahnya pastilah tak pernah membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ayahnya telah bertekad mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela negeri dan bangsa ini tanpa pamrih sekalipun. Baginya, ayah merupakan cermin keberanian. Dan ibu, ibu adalah teladan kasih sayang. Ia merupakan sosok yang penuh welas asih, berjiwa besar, dan penyabar. Setelah kematian ayahnya, ia ingat bagaimana ibunya senantiasa menjaganya dengan keagungan dan ketabahan jiwa seorang perempuan hingga akhir hayatnya. Bagai pengorbanan Kunti kepada anak-anaknya: para Pandawa.
Kenangan itu pun menghilang. Di antara keragu-raguan, ia menyalakan sebatang lilin putih. Kadang seberkas cahaya bisa menjadi semacam pelepas ketegangan kala kegelapan tak lagi mampu untuk mengusir resah. Namun, dengan cahaya itu, ia tak juga mampu mengenal apapun. Telah lama, begitu lama sekali ia merasakan itu. Mungkin sejak rasa itu hilang. Sebuah perasaan yang tak pernah ia percayai hingga kini. Perasaan yang menghempasnya di antara penderitaan akan luka dan pedih yang sangat dalam. Tetapi, ia sepertinya enggan untuk menjelma pertapa dan menjalani hidup yang masokis. Sebagaimana kesadarannya yang tak pernah mengijinkannya untuk terus-menerus berputus asa.
“Buatkan aku sekuntum bahagia!” Ia mencoba untuk bicara.
Bahagia? Tiba-tiba ia tersadar dan mencoba merenungi kata-katanya sendiri. Bukankah bahagia itu hanyalah sebuah lelucon konyol tentang hidup yang sesungguhnya hanya semu belaka. Ah, ia mungkin tak ingat lagi apa yang pernah dikatakannya dulu tentang bahagia. Sambil berpikir tajam, jari tangannya tanpa sengaja menekan tombol huruf T. Sementara ia sendiri tetap bergumam dengan kata bahagia. Mencari-cari jawaban yang tak pernah ia punyai. Namun, tatap matanya tetap menerawang, seakan menembus setiap batas realita. Hingga sepersekian detik kemudian ia kembali tersadar. Ia paham bahwa miliaran mimpinya pun pasti tak akan pernah mampu memahami apa arti bahagia, sebab ia tak pernah mampu benar-benar merasakannya, baik di masa lalu, kini, atau di masa yang akan datang sekalipun.
Lalu, apakah yang selama ini ia tunggu? Ia sendiri pun sebenarnya tak pernah mencoba untuk mengerti. Ruang yang masih tetap kosong dan lembab, lembaran puisi yang berserakan, dan layar komputer dengan deretan empat buah huruf yang tertera di dalamnya, menunjukan apa yang telah dicapai dan di jalaninya selama ini: sebuah romantisme hidup yang penuh fatamorgana. Benarkah itu semua yang ia cita-citakan selama ini? Tak pernah ada yang tahu. Sementara deretan empat huruf di layar komputer itu sepertinya menunjukan sesuatu. Dan tiba-tiba sebuah huruf baru pun muncul, entah dari mana datangnya, menambah deretan huruf itu menjadi lima buah. Huruf A berada paling akhir setelah huruf C, I, N, dan T. Kemudian kelima huruf itu pun terlihat bercahaya. Sungguh, sebuah keanehan yang mistis. Apakah deretan huruf itu mengungkapkan sesuatu? Kini ia tak akan pernah mampu lagi untuk menjawab. Selamanya hanya diam, diam, dan diam, menuju kesunyian yang paling dalam.
Bandung, 07122003, 04:00
“Ia pergi dan tak akan pernah kembali,” lirihnya.
Seperti ada semacam keberanian yang menyelinap di antara aliran darahnya. Jari-jari kurusnya yang selalu bergetar itu kini mulai bergerak. Tombol huruf C di atas papan keyboard ditujunya. Sepermilimeter lagi jari-jari itu akan sampai, namun tiba-tiba terhenti dan kemudian ditariknya kembali. Keengganan bergemuruh di dadanya yang hampa. Ia kembali terjelembab. Matanya bergetar. Kesedihan itu rupanya telah merasuk dalam. Tetes-tetes airmata pun kini menggembang. Sebuah kata tentang luka mengingatkannya akan kisah masa lalu yang pedih. Tubuhnya kini meringkuk. Kedua lutut ia rekatkan, kepalanya ia benamkan dalam isak tangis yang sendu. Walaupun jauh di lubuk hatinya, ia telah merasa malu untuk terus-menerus bersedih.
Tiba-tiba tangisnya terhenti. Ada amarah yang berkilat di matanya. Wajah angkuhnya ia tegakkan. Tubuhnya pun bagai diguncang gempa yang hebat. Di antara denting-denting waktu, ia berteriak keras, menggetarkan dinding-dinding kamar yang telah lama kosong dan lembab. Dan turut pula memecah malam di luar sana, yang kini lelap dengan dinginnya angin malam yang berhembus tajam.
“Persetan dengan airmata!” serunya pada diri sendiri.
Namun akankah ia mengerti bahwa ada sesuatu yang hingga kini tak bisa ia ingkari, dan sampai kapanpun tak akan pernah bisa ia ingkari. Sesuatu yang mengganjal di lelap mimpinya. Semacam ombak yang senantiasa bergulung menghantam pantai. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar airmata dan kesedihan: kenyataankah? Entah.
Kesendirian ini tentunya hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah kini tak ada lagi yang rela untuk menampung segenap asa dan kerinduannya itu. Kesendirian yang begitu rapi ia simpan di setiap hembusan nafasnya yang nestapa. Dan kesendirian, baginya kini ialah pintu kamar yang terkunci rapat, jendela yang terpaku, lubang ventilasi yang terisolasi, dan tentunya suara yang terbungkam, juga segala sesuatu yang hanya bisa ia nikmati sendiri.
Tajam tatapnya kembali menuju layar komputer. Harus ada yang terselesaikan, pikirnya. Tanpa terasa bulatan putih matanya kian memerah. Seperti bara api yang senantiasa menyimpan amarah. Lalu hamparan puisi yang sedari tadi berceceran di sekitarnya, diraihnya kembali. Dengan beringas ia tampak mencari-cari. Pikirannya menyeruak suasana.
“Kata…kata…kata…kata…,” ucapnya pada hamparan puisi itu.
Ia menemukan sesuatu, ya, sesuatu. Selembar puisi diraihnya erat-erat. Lalu dibacanya pula dalam diam. Bibir keringnya tampak gemetar. Ia pun memejamkan mata. Pikirannya seperti tengah meresapi mantra-mantra yang hakiki. Absurditas yang biasa ia puja di setiap aliran waktu. Keliaran imajinasi yang pasti akan membawanya ke dalam ruang di mana realita dan sesuatu yang semu seakan tiada bedanya. Tubuh kasarnya terdiam tanpa gerak. Bahkan mungkin tanpa nafas, tanpa denyut nadi, dan tanpa detak jantung sekalipun. Namun wajahnya menampakan ketenangan, didekap kehampaan yang paling sublim. Sekali lagi, sebuah kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Keheningan yang kian menggelora, tapi ia sama sekali tak merasa kehilangan apapun. Hanya sebuah keterasingan yang lepas dari sebuah rutinitas hidup, teramat merdeka, tak terjajah oleh sesuatu.
Perlahan-lahan kini pelupuk matanya membuka. Jiwanya seakan baru saja terlahir kembali dari sebuah rahim bernama sunyi, yang telah mengandungnya selama berabad-abad. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sungguh, kegelisahannya kini mereda sesaat. Seperti kemarau di tengah gurun sahara yang gersang, tiba-tiba terguyur hujan lebat yang menyejukan.
“Sebait puisi,…ah, tidak! Aku telah terlalu lelah dengan puisi. Namun apalagi kini yang harus aku renungi. Oh, Tuhan, jangan biarkan aku senantiasa terpuruk di dalamnya…” kata-katanya terhenti seketika.
Dipandanginya layar komputer kembali. Ia tersentak. Ada huruf C terpampang di lembaran putih komputernya. Aneh, ia merasa belum sempat untuk menekan tombol huruf C. Namun, kini tidak ada waktu untuk bertanya-tanya lagi. Jawaban telah menjelma labirin-labirin hampa di otaknya. Tanpa sadar, jari telunjuknya kini telah menekan tombol huruf C dengan kelelapan yang panjang. Terpampanglah seketika deretan huruf C yang berjejer rapi. Setelah sampai pada baris kedua, ia baru tersadar.
“Oh, apa yang telah kulakukan?” sesalnya pada diri sendiri.
Sebenarnya sesal ialah sesuatu yang teramat ia benci. Baginya, sesal hanyalah perbuatan bodoh manusia. Pertanda ketidakyakinan atas apa yang telah dilakukan, ketidaksadaran atas setiap resiko yang hadir di setiap langkah kehidupan, dan semacam ketidakmampuan menerima segala ketentuan yang telah digariskan oleh Sang Penentu. Sementara waktu, toh, tak pernah bisa berbalik arah, lalu untuk apa manusia harus merasa menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Namun, pendiriannya kini adalah semacam konsekuensi dari luka yang pernah dideritanya di masa lalu. Ia tiba-tiba teringat pada suatu masa di mana ia pernah mengalami sebuah penyesalan yang begitu mendalam. Sebuah kisah yang melankolis, tetapi berakhir dengan goresan derita hingga seumur hidupnya. Tentang seorang perempuan berwajah hujan, tentang cinta yang pernah bersemi, tentang dahaga dan hampa yang terpuaskan, tentang kemesraan yang mendesah, dan tentang sebuah pelukan yang senantiasa hangat. Sekian lama ia terbuai di dalamnya, larut di antara kesyahduan yang membunga. Sehingga suatu kali, pernah juga ia banyak mengucap puji syukur kepada Tuhan karena telah sudi menciptakan makhluk bernama perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Bukankah satu sama lainnya tak pernah bisa hidup sendiri. Namun, realita sepertinya tak pernah memihak pada manusia semacam dirinya. Harapan yang tak sejalan dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, perempuan yang telah sekian lama dipujanya itu, tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali. Entah kemana dan mengapa.
“Kesetiaan rupanya tak pernah bisa benar-benar bermakna,” ucapnya waktu itu, di antara waktu yang berguguran.
Ketabahannya roboh seketika. Penyesalan perlahan-lahan menyusupi denyut nadinya, desah nafasnya, detak jantungnya, bahkan setiap helai jiwanya. Ia menyesal telah terbuai bujuk perasaan yang seharusnya tak patut ia percayai. Dan ia pun menyesal karena telah mengabaikan bisik logika yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Itulah di mana ia pernah merasakan penyesalan untuk yang pertama kalinya dan sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya, ia pun menyesal karena telah merasa menyesal. Sejak itulah, ia mengasingkan diri, mencoba memahami kembali segalanya dengan meresapi segenap kesendirian dan sunyi.
Layar komputer masih menunggunya untuk berkata. Ada bisik hati yang menuntun jari telunjuk kanannya untuk menekan tombol huruf I. Sejenak pikirannya bimbang akan sesuatu. Dan kini, ia teramat merasa ragu-ragu. Seribu pertanyaan pun berkecamuk: mengapa harus huruf I, mengapa tidak huruf yang lain saja, ada apa dengan huruf I, begitu berartikah huruf I, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun ia terlambat, sebuah kekuatan asing menarik jari telunjuk kanannya untuk menekan tombol huruf I. Akhirnya terpampanglah di layar komputer, huruf I yang tegak dengan angkuhnya.
“Mengapa aku tak pernah mampu untuk mengeja hidupku sendiri,” teriaknya dalam kekesalan.
Lembaran puisi yang berserakan, layar komputer yang mengambang, ruang yang kosong, dan kesendirian yang hampa, menggambarkan kepedihannya yang semakin meraja. Pernah pula ia berspekulasi, mencoba untuk mengerti arti hidup melalui 1001 jalan kematian.
“Bukankah setiap yang hidup itu pasti mati. Lalu untuk apalagi aku menundanya, jika hidup pun aku serasa mati,” ujarnya saat itu.
Karena itu, beberapa kali ia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri, baik itu dengan terjun bebas dari ketinggian puluhan meter tanpa pengaman dengan kepala berada di bawah, membakar tubuhnya sendiri dengan guyuran bensin, meminum racun yang paling mematikan, menggantung lehernya di tiang gantungan, menenggelamkan diri di lautan, menusuk jantungnya dengan senjata tajam, maupun menembak kepalanya dengan pistol sungguhan. Namun Tuhan sepertinya belum berkehendak ia mati. Dan setiap kali percobaan bunuh diri itu dilakukannya, setiap kali pula ada keajaiban yang membuatnya masih tetap hidup. Dalam kegagalannya, akhirnya ia pun tersadar bahwa terlalu bodoh bagi dirinya untuk sekadar berputus asa, naif, dan sia-sia.
Ia kemudian kembali teringat pada lembaran puisi yang berserakan itu. Dipandanginya satu persatu dengan cermat. Mungkin ada jutaan huruf, ribuan kata, dan ratusan kalimat di sana. Adakah yang paling istimewa di antaranya, pikirnya. Tanpa sadar, ada sebuah huruf yang paling menggoda tatapnya di antara jutaan huruf, ribuan kata, dan ratusan kalimat itu. Ia menemukan huruf N, ya, huruf N. Baginya, huruf itu begitu memesona, entah mengapa. Tanpa ragu lagi, sebuah jari tangannya digerakkan menekan tombol huruf N, maka tercetaklah di layar komputer itu huruf N, setelah huruf C dan I.
Walaupun begitu, ia masih merasa kehilangan sesuatu. Seketika terbersit keinginannya untuk mengadu, tapi pada siapa, pada apa, dan mesti bagaimana. Sesungguhnya ada dua tempat yang pernah menjadi tempatnya mengadu. Pertama, yaitu perempuan yang kini telah pergi dan tidak akan pernah kembali itu. Sementara yang kedua adalah orang tua kandungnya yang juga kini telah tiada. Tentang kedua orang tuanya, ia banyak mengenang, yaitu masa ketika kedua orang tuanya masih selalu berada di sampingnya, melindunginya, menyayanginya, dan senantiasa membuatnya berarti. Ayahnya ialah seorang pejuang. Ia gugur ketika melawan penjajah, namun jasadnya tidak berada di taman makam pahlawan karena pemerintah tidak pernah berani mengakuinya sebagai pahlawan. Tapi walau bagaimanapun, ia yakin bahwa ayahnya pastilah tak pernah membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ayahnya telah bertekad mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela negeri dan bangsa ini tanpa pamrih sekalipun. Baginya, ayah merupakan cermin keberanian. Dan ibu, ibu adalah teladan kasih sayang. Ia merupakan sosok yang penuh welas asih, berjiwa besar, dan penyabar. Setelah kematian ayahnya, ia ingat bagaimana ibunya senantiasa menjaganya dengan keagungan dan ketabahan jiwa seorang perempuan hingga akhir hayatnya. Bagai pengorbanan Kunti kepada anak-anaknya: para Pandawa.
Kenangan itu pun menghilang. Di antara keragu-raguan, ia menyalakan sebatang lilin putih. Kadang seberkas cahaya bisa menjadi semacam pelepas ketegangan kala kegelapan tak lagi mampu untuk mengusir resah. Namun, dengan cahaya itu, ia tak juga mampu mengenal apapun. Telah lama, begitu lama sekali ia merasakan itu. Mungkin sejak rasa itu hilang. Sebuah perasaan yang tak pernah ia percayai hingga kini. Perasaan yang menghempasnya di antara penderitaan akan luka dan pedih yang sangat dalam. Tetapi, ia sepertinya enggan untuk menjelma pertapa dan menjalani hidup yang masokis. Sebagaimana kesadarannya yang tak pernah mengijinkannya untuk terus-menerus berputus asa.
“Buatkan aku sekuntum bahagia!” Ia mencoba untuk bicara.
Bahagia? Tiba-tiba ia tersadar dan mencoba merenungi kata-katanya sendiri. Bukankah bahagia itu hanyalah sebuah lelucon konyol tentang hidup yang sesungguhnya hanya semu belaka. Ah, ia mungkin tak ingat lagi apa yang pernah dikatakannya dulu tentang bahagia. Sambil berpikir tajam, jari tangannya tanpa sengaja menekan tombol huruf T. Sementara ia sendiri tetap bergumam dengan kata bahagia. Mencari-cari jawaban yang tak pernah ia punyai. Namun, tatap matanya tetap menerawang, seakan menembus setiap batas realita. Hingga sepersekian detik kemudian ia kembali tersadar. Ia paham bahwa miliaran mimpinya pun pasti tak akan pernah mampu memahami apa arti bahagia, sebab ia tak pernah mampu benar-benar merasakannya, baik di masa lalu, kini, atau di masa yang akan datang sekalipun.
Lalu, apakah yang selama ini ia tunggu? Ia sendiri pun sebenarnya tak pernah mencoba untuk mengerti. Ruang yang masih tetap kosong dan lembab, lembaran puisi yang berserakan, dan layar komputer dengan deretan empat buah huruf yang tertera di dalamnya, menunjukan apa yang telah dicapai dan di jalaninya selama ini: sebuah romantisme hidup yang penuh fatamorgana. Benarkah itu semua yang ia cita-citakan selama ini? Tak pernah ada yang tahu. Sementara deretan empat huruf di layar komputer itu sepertinya menunjukan sesuatu. Dan tiba-tiba sebuah huruf baru pun muncul, entah dari mana datangnya, menambah deretan huruf itu menjadi lima buah. Huruf A berada paling akhir setelah huruf C, I, N, dan T. Kemudian kelima huruf itu pun terlihat bercahaya. Sungguh, sebuah keanehan yang mistis. Apakah deretan huruf itu mengungkapkan sesuatu? Kini ia tak akan pernah mampu lagi untuk menjawab. Selamanya hanya diam, diam, dan diam, menuju kesunyian yang paling dalam.
Bandung, 07122003, 04:00
Subscribe to:
Comments (Atom)




